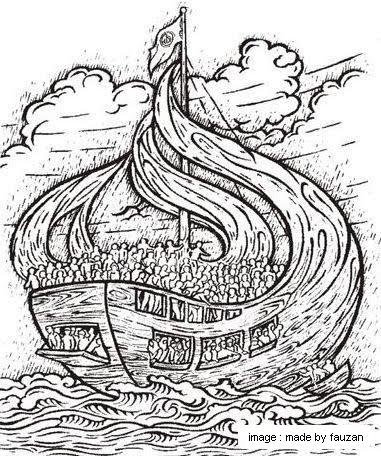Petunjuk bagi Mukminin Agar Selamat Berpulang
Menyimak Argumen Ali as “Taklukan” Kaisar Romawi
Oleh : Abdul Choliq Wijaya
Diriwayatkan dari himpunan buku bertajuk saluni qobla antafqiduni, susunan Muhammad Ridha Al-Hakimi (Muassasah Al-A’lami, Beirut, 1399 H) bahwa sorang Kaisar Romawi begitu antusias untuk mengetahui tentang kedalaman ilmu Islam. Di sisi zaman dan kondisi yang berlainan, para kiai (ulama) unggulan kita di Indonesia pun kini sibuk menerima kunjungan para calon presiden yang memohon restu. Ada baiknya kemungkinan argumentasi Ali as menyibak “rasa ingin terpilih” para kandidat Presiden Indonesia 2009 ini.
Sang kaisar lalu menulis surat kepada seorang khalifah di jazirah Arabia, seperti disebutkan oleh Ibnu Musayyib dari Kaisra Bani al-Asfar kepada kalifah pemerintahan Islam di jazirah Arabia. Aku ingin bertanya kepada anda mengenai sejumlah pertanyaan pokok yang mengusikku selama ini. Maka, beritahukanlah kepadaku mengenai hal-hal itu, yakni:
1. Apa sesuatu yang tidak Allah ketahui? Apa sesuatu yang tidak Allah miliki? Apa sesuatu yang semuanya mulut? Apa sesuatu yang semuanya kaki? Apa sesuatu yang semuanya mata? Apapula sesuatu yang semuanya sayap?
2. Beritahukan kepadaku tentang seseorang yang tidak memiliki kerabat, mengenai empat mahluk hidup yang tidak pernah berada di dalam rahim, juga tentang sesuatu yang bernafas tetapi tidak bernyawa. Apa pula yang diteriakkan ”terompet” Naqus di hari kiamat, tentang sesuatu yang hanya sekali terbang mengenai pohon yang menaungi setiap pengendara di saat bepergian selam seratus tahun, yakni suatu perjalanan yang tidak pernah ditempuh dunia.?
3. Ya khalifah, jelaskan pula tentang tempat yang tidak pernah disinari cahaya matahari kecuali sehari saja. Terangkan pula tentang sebuah pohon yang tumbuh tanpa air, mengenai sesuatu yang menyerupai penghuni surga – jika ia makan dan minum, ia idak membuang hajat besar atau kecil?
4. Jelaskan pula ya khalifah Allah SWT, jika engkau benar utusan-Nya, tentang sesuatu yang mirip dengan meja-meja di surga dan di atasnya terdapat hidangan-hidangan di mana di setiap hidangan memiliki warna-warna yang tidak bercampur. Coba pula terangkan kepadaku mengenai sesuatu yang keluar dari buah apel dan mirip dengan bidadari surgawi yang konon tiada pernah beruba. Jelaskan pula mengenai kenikmatan di dunia sementara ini yang bisa dirasakan dua orang, namun di akhirat hanya untuk satu orang. Jangan lupa ya khalifah, terangkan kepadaku mengenai kunci-kunci surga itu!
Saat khalifah menerima surat Kaisar Romawi, beliau memohon agar sayydini Ali bin Abi Thalib as untuk menuliskan jawabannya.
Dengan nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Amma ba’du. Aku (Ali bin Abi Thalib as) telah membaca surat Anda wahai Raja Eomawi dan aku kini membalasnya dengan bantuan dan bimbingan Allah SWT, serta berkat Nya dan berkah yang selalu menyertaiku dari Nabi Muhammad SAW.
Adapun sesuatu yang Allah SWT tidak ketahui adalah keyakinan Anda, wahai raja Romawi bahwa Dia punya anak, istri dan sekutu. Ketahuilah Raja, Allah SWT sudah menegaskan dalam Al Quran bahwa Allah SWT tidak punya anak dan Tiada Tuhan lain di samping Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. (Q. S. Al-Ikhlas : 3)
Sesuatu yang tidak dimiliki Allah adalah kezaliman. “Dan tidaklah Tuhanmu itu berbuat kezaliman terhadap hamba-hambaNya (3: 182). Sesuatu yang semuanya mulut adalah api yang melahap segala sesuatu yang dilemparkan kepadanya. Adapun yang semuanya kaki adalah air. Yang semuanya mata adalah matahari. Yang semuanya sayap adalah angin. Yang tidak memiliki kerabat adalah Nabi Adam as, domba Nabi Ibrahim as, dan Siti Hawa.
Sementara itu, yang bernafas tanpa nyawa adalah subuh. Allah SWT berfirman, “Demi shubuh di saat bernafas” (81 : 18)
Teriakan “terompet” Naqus adalah thoqqon,thoqqon- thoqqon, thoqqon-thoqqon, mahlan-mahlan, shidqon-shidqon. Sesungguhnyalah dunia telah memperdaya dan merayu kita. Dunia berlaku dari abad ke abad. Tidaklah suatu haripun berlalu dari abad ke abad. Tidaklah suatu haripun berlalu melainkan kekuatan fisik kita semakin melemah. Sesungguhnyalah saat-saat kematian telah memberitahu kepada kita, kita akan ”pergi dan bermukim”. Kembali ke kebaqaan, yakni jika berkeinginan pulang abadi dengan selamat, aku adalah satu-satunya ”petugas penjaga” gerbang kembali kepada Sang Pencipta Allah SWT.
Perlu engkau ketahui Raja Romawi, setelah Rasulullah saw, akulah (Ali bin Abi Thalib) pemegang ilmu kembali dengan selamat (Ilmu Syathariyah) kepada-Nya dan sesuadhku adalah para penggantiku (menurut silsilah Imamah Wasilah/Wasithah) yang terus gilir berganti digengang oleh Wasi yang berhak dan sah seizin-Nya di setiap zaman hingga Allah SWT memproklamasikan kiamat.
Para wasithah itulah yang sering disebut-sebut oleh Rasul SAW, bahwa mereka bukanlah termasuk Rasul atau Nabi, namun di sisi Allah SWT merekalah yang di hari akhir nanti cahayanya begitu mencorong gilang gemintang di antara umat Ku yang terpilih (Hadits Sahih Ghadir Qum).
Hai kaisar, yang terbang hanya sekali adalah Gunung Thuri Sina. Di saat Bani Israil bermaksiat, Allah SWT mengambil sebidang tanah dari Thuri Sina dan membuat untuk mereka berdua sayap dari cahaya lalu menjatuhkkannya di atas mereka. Padahal, perjalanan dari Thuri Sina ke Baitul Maqdis membutuhkan beberap hari. Sehubungan dengan hal itu, Allah SWT berfirman, ”Dan ingatlah ketika kami angkat gunung dai atas mereka seakan-akan naungan awan” (Q.S. Al-A’raf : 171).
Tempat yang hanya sekali disinari matahari adalah dasar laut yang terbelah bagi kelapangan jalan Nabi Musa as. Air terbelah dan berdiri menjulang laksana gunung dan dasarnya menjadi kering karena disinari matahari, kemudian air itu kembali seperti semula, tutur Ali as dalam surat balasannya.
Pohon yang seseorang berjalan di bawahnya selama seratus tahun adalah Pohon Tuba, yakni Sidratul Muntaha di ”langit ke tujuhNya”. Padanya berakhir amal perbuatan keturunan Nabi Adam as. Ia termasuk dari pohon-pohon surgawi, tidak ada di surga suatu istana atau rumah, melainkan ada padanya suatu ranting-ranting pohon tersebut. Yang serupa dengan itu adalah matahari, sumbernya satu, namun cahayanya berada di setiap tempat, sebagimana yang dikehendaki Allah SWT.
Mengenai pohon yang tumbuh tanpa air, adalah pohon yang merupakan mujijat beliau (Rasulullah SAW). Allah SWT berfirman, ”Dari kami tumbuhkan untuknya (Muhammad) pohon dari yaqthi (sejenis buah labu). (Q.S. As-Shaffat : 146)
Adapun yang menyerupai surgawi di dunia fana ini, ya Kaisar Roamwi, menurut ilmu kami kaum mukminin yang berada dalam Hidayah-Nya adalah janin dalam perut ibunya. Dia makan dan minum melalui pusar ibundanya, tetapi dia tidak buang air kecil ataupun buang air besar.
Yang menyerupai warna-warna dalam satu hidangan di surga adalah telur yang di dalamnya terdapat dua warna, yaitu putih dan kuning, namun keduanya tidaklah bercampur aduk. Yang menyerupai bidadari surgawi adalah ulat yang keluar dari buah apel dan tidak berubah.
Berkaitan dengan maksud akan sesuatu yang di dunia dimiliki dua orang, sedang di akherat cuma berhak dimiliki seorang saja adalah kurma. Di dunia fana ini ia dimiliki orang mukmin seperti aku dan orang fasik atau kafir sebagaimana adanya engkau, ya Raja Romawi. Namun di akherat nanti, sebagaimana ketentuan Allah SWT, kurma hanya diberkahkan kepada orang mukminin sebab hanya kaum mukminin yang boleh masuk surga-Nya, sedangkan kalian tidak diperkenankan.
Tentang pencarian orang Romawi akan kunci surga, akan kutunjukkan, yakni, ”Tiada Tuhan selain Allah SWT, dan Muhammad saw adalah Rasulullah”.
Berkenaan dengan isi surat balasan ayidina Ali bin Abi Thalib as ini dikisahkan oleh Ibnu Al Musayyib, seperti dinukil oleh Muhammad Ridha Al Hakimi, sang Kaisar Romawi bereaksi dengan berkata, ”Penjelasan ini tidaklah akan keluar keculai dari rumah kenabian yang disucikan-Nya”
Kemudian Kaisar Romawi menanyakan siapa gerangan orang yang menuliskan surat balasan untuknya, lalu diperoleh keterangan dari stafnya, bahwa surat balsan itu ditulis oleh putra paman Rasulullah saw. Kaisar Romawi pun bergegas menulis surat balasannya yang langsung ditujukan kepada sayidina Ali bin Abi Thalib as.
”Salam atasmu”. Aku telah membaca isi jawabanmu dan aku yakin, bahwa anda berasal dari rumah kenabian, sumber kerasulan dan anda pun adalah seorang pemberani serta berilmu. Aku harap anda dapat menjelaskan pendapat anda tentang yang disebutkan Allah dalam kitab kalian, yang firman-Nya mengatakan, ”Dan mereka bertanya tenatgn roh. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku” (Q.S. Al _Isra : 85)
Kemudian Sayidina Ali menjawab tatentang kepenasaran Kaisar Romawi. ”Dengan permohonan izin Tuhanku Allah SWT, bahwa roh adalah sesuatu yang maha halus dan pancaran Cahaya Yang Mulia, ciptaan pencipta-Nya dan kekuasaan pembuat Nya yang tidak ada lagi sesuatupun Zat Mulia dan Agung serta Mahakuasa selain dia. Roh itu dikeluarkan dari khazanah-khazanah kerajaan-Nya dan ditempatkan di kerajaanNya pula. Bagi Nya roh adalah sebab atau asal-usulmu dan bagimu roh adalah titipan-Nya. Jika anda mengambil milikmu dari Allah, maka Ia akan mengambil milikNya darimu. Wassalam.”
Demikian kecerdasan Ali as dengan segala hidayah yang dilimpahkan-Nya sehingga seorang ilmuan kristiani George Jordac menyimpulkan bahwa Alilah satu-satunya dari sahabat Rasul saw yang dari sejak dini menyelami lautan kebijakan Islam di bawah bimbingan langsung sang tutor Ilahi, Muhammad SAW. Tak ayal lagi, kearifan, kecerdasan, kesalehan, dan keluasan pengetahuannya merupakan refleksi sang penutup zaman, Rasulullah saw.
”Ali bin Abi Thalib adalah sumber pengetahuan yang paling utama. Tak satupun cabang ilmu pengetahuan di Negeri Arab yang tidak diketemukan dan dipelopori Ali as, ”tutur Geoge Jordac. Tak pelak lagi, Kaisar Romawi pun dibuatnya skak mat. Bagaimana pula dengan hasrat yang dikandung oleh kandidat Presiden Indonesia 2009? Siap diuji oleh metodologi Ali as?.
Ditulis ulang oleh Elan Suherlan
Kamis, 02 September 2010
Kamis, 29 April 2010
IMAM ALI SETELAH WAFAT RASULULLAH SAW
Oleh : DR. Khozin Affandi
Setelah Rasulullah saw wafat, Abu Bakar dibai’at menduduki jabatan khlaifah setelah melalui pertentangan antara kaum Anshar dengan kaum Muhajirin. Ditulis oleh Al-Mas’udi dalam kitabnya “Murujud-Dhahab” juz 2,halaman 307,bahwa Imam Ali dan Bani Hasyim tidak turut membai’at Abu Bakr. Mereka baru memberikan bai’at kepada Abu Bakr setelah Siti Fatimah wafat (enam bulan setelah Rasulullah saw wafat). Sebelum wafat, Siti Fatimah berpesan kepada suaminya (Imam Ali) agar jenazahnya dikubur secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui siapapun. Memenuhi pesan istri sekaligus putri kesayangan Rasulullah Muhammad saw,Imam Ali menguburkan jenazah istrinya di malam hari dan tidak diketahui siapapun. Sampai sekarang sejarah hanya mengatakan bahwa makam Siti Fatimah majhul (tidak diketahui).
Apapun yang terjadi pada waktu itu, yang jelas setelah Abu Bakr menduduki tampuk kekhilafahan Imam Ali bin Abu Thalib tetap berupaya memperjuangkan hak dan kebenaran dirinya untuk menjadi pengganti Rasululah saw sesuai wasiat beliau tentang Maula. Namun kondisi ini malah berubah menjadi polemik. Karena itu untuk menghindari kondisi menjadi keruh dan menjaga keberadaan umat Islam, Imam Ali mengambil sikapnya yang khas.
Setelah semua kejadian tersebut, Imam Ali bin Abi Thalib menyendiri dan melanjutkan kehidupan pribadinya. Disamping masalah bai’at, penguasa saat itu menghendaki Ali untuk tidak menyuarakan hak dan kebenarannya sebagai pengganti Nabi saw. Pihak penguasa juga menghendaki agar Imam Ali ikut serta menghunus pedang berperang untuk memperkuat Kekuasaan penguasa melawan musuh dan orang-orang yang murtad. Untuk per mintaan ini Imam Ali menolak. Atas sikap seperti ini, penguasa memandang wajar jika harus mengabaikan dan merendahkan beliau di mata umum. Dan politik ini juga yang menambah keterasingan beliau di tengah masyarakatnya. Di sisi lain, kaum Quraisy pun bersikap tidak peduli terhadap nasib Imam Ali.
Dalam suatu doanya, Imam Ali mengadukan sikap kaum qurays,”Ya Allah, aku meminta pertolonganmu dari orang-orang Quraiys dan siapapun yang mendukung mereka. Sesungguhnya mereka telah memutus tali hubungan kekerabatan denganku, meremehkan posisiku dan bersepakat memerangiku karena satu hal yang merupakan milikku.”
Jadi disamping menghadapi siasat pemegang kekuasaan saat itu, beliau juga harus berhadapan dengan sukunya sendiri yakni suku quraiys yang juga tidak bersahabat dengan beliau.
“Ya Allah, aku menangis dan tak seorangpun yang menolong dan membelaku kecuali orang-orang khususku, yang mana aku tidak sampai hati membawa mereka sampai titik kematian …”.
Doa pengaduan di atas sudah cukup untuk membaca politik kekuasaan para khalifah saat itu dan sikap kaum quraiys kepada beliau.
Khalifah Umar bin Khattab menjelang akhir kepemimpinannya mengangkat dewan syura terdiri dari enam orang untuk memilih khalifah setelah dia. Dia juga berpesan manakal terjadi perselisihan maka hendaklah berpegang pada kelompok yang di dalamnya ada Abdur Rahman bin Auf. Dewan Syura adalah :
- Ali bin Abi Thalib (dari Bani Hasyim)
- Usman bin Affan (Bani Umayah)
- Abdurrahman bin Auf (Bani Zuhrah)
- Sa’ad bin Abi Waqash (Bani Zuhrah)
- Thalhah bin Ubaidillah (Bani Tamim)
- Zubair bin Awwam, suami Asma’ binti Abu Bakar saudari Siti Aisyah binti Abu Bakr. Jadi ada hubungan kekerabatan antara Zubair dan Siti Aisyah. Karena itu ketika Zubair mengadakan pemberontakan kepada khalifah Ali bin Abi Thalib yang baru saja dibai’at sebagai Khalifah, Siti Aisyah membantu Zubair bin Awwam.
Dalam Syarh Nahjul Balaghah Imam Ali pernah mengingatkan dewan syura untuk lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan yang mendalam dalam mengambil keputusan memilih khalifah agar tidak menyesal di kemudian hari. Tetapi Dewan lebih memilih perkataan Umar bahwa “Ali ra.adalah seorang yang suka bercanda, sebuah karakter yang sangat menyakitkan Ali bin Abi Thalib karena perkataan itu diungkapkan dengan nuansa negatif. Kata-kata Umar inilah yang menjadi alasan bagi Mu’awiyah dan Amr bin ‘Ash di kemudian hari dengan mengatakan “Ali suka bermain-main” dalam pengertian sebagai orang yang tidak bersungguh-sungguh. Dengan berbagai upaya,Imam Ali melakukan pembelaan diri meski itu tidak membantu apa-apa.
Kamis, 01 April 2010
Lanjutan Syahadat
Akan tetapi potensi positif manusia yang berupa fitrah murni kemanusiaannya terus ikut menyertainya dalam kehidupan di dunia ini. Dan kenyataan ini bisa dilihat dalam rentang perjalanan sejarah yang panjang dan dalam perkembangan peradabannya yang mengatakan bahwa manusia tidak pernah berhenti membahas atau mencari Tuhan sebagimana dikerjakan oleh beberapa filosof, atau membuat konsep dan penjelasan-penjelasan tentang Tuhan sebagaimana dikerjakan para pemimpin agama, atau meyakini bahwa ada kekuatan gaib di balik alam ini sebagimana pada kebudayaan kuno.
Di samping faktor intern-fitrah, faktor-faktor eksternal turut mendorong manusia mencari kekuatan ghaib itu. Dalam hidup di atas bumi ini, manusia dihadakan dengan lingkunan alami yang seringkali tidak ramah terhadap nasib mereka seperti banjir, gempa bumi, halilintar, wabah penyakit, serangan hama, gunung meletus, dan lain-lain gangguan alam yang setiap saat dan dengan tiba-tiba mengancurkan harapan mereka. Pada sisi internal, mereka memiliki sebuah rencana, cita-cita, ambisi, kepentingan, nafsu keinginan bahkan sifat-sifat tamak, serakah, zhalim, dan sejumlah sifat-sifat lainnya yang bisa berdampak merugikan orang lain atau pihak-pihak lain.
Berkembangnya faktor internal-fitrah ini didasarkan atas fakta potensial, atau natural faculties (kemampuan alami), meminjam istilah John Locke yang menolak teori innatea idea platonis, yang dimiliki manusia. Kemampuan alami yang dimiliki manusia itu adalah panca indera dan akal rasio. Kemampuan inilah yang dipakai dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi cita-cita, ambisi, kepentingan dan kebutuhan sehari-hari, namun ia juga bisa diasah dan dipertajam melalui pendidikan kehalian dan keterampilan untuk melakukan observasi ilmiah, merumuskan hipotesis, mengujiknya lewat eksperimen, guna melahirkan atau membuktikan kebenaran teori, atau untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan lain yang terpendam di balik alam. Hasilnya adalah peradaban modern sebagaimana kita saksikan ini lengkap dengan segala produk dan temuan teknologi di sektor kehidupan mulai dari bumbu masak sampai ruang angkasa.
Keadaan inilah yang dikonsepsikan oleh Auguste Comte sebagai tahap positive atau tahap ilmiah di mana simpulan empirik dan kalkulasi rasio memainkan peranan penting sekaligus menyingkirkan cara berfikir tahap teologis dan tahap metafisik dari percaturan peradaban karena tidak diperlukan lagi. Boleh jadi Comte tidak pernah memperhitungkan konsekuensi praktis yang tidak jarang menyimpang dari perhitungan dan rancangan manusia. Peluncuran pesawat ruang angkasa yang sudah dirancang dengan teknologi tinggi tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba terjadi kebocoran di pabrik nuklir atau bahkan meledak dan meluluh lantakkan bangunan dan memakan korban jiwa. Tiba-tiba terjadi angin puting beliung yang melumatkan bangunan yang super canggih dan tidak mampu dikendalikan oleh teknologi manusia. Tiba-tiba terjadi gempa bumi atau gunung meletus dengan kekuatan yang dahsyat memakan habis bangunan dan menelan manusia. Atau bahkan tangan-tangan manusia itu sendiri yang membuat kerusakan secara langsung. Tiba-tiba terjadi kontak senjata, terjadi peperangan, terjadi permusuhan manusia oleh manusia, terjadi amuk masa, terjadi pembunuhan secara masal atas nama doktrin kiamat dalam suatu sekte tertentu dan masih banyak kasus-kasus lain yang tak mungkin diturunkan di sini semuanya. Memang harus diakui bahwa manusia dengan kemampuan akal, teori dan teknologi yang dikuasainya bias membuat rancangan ke depan, akan tetapi tetap saja berlaku premis dasar yang menyatakan bahwa masa depan adalah ibarat sebuah gudang yang menyimpan seribu ketidakpastian. Dalam kemasan agama, ungkapan bijak itu menyatakan manusia berusaha, namun Tuhanlah juga yang menentukan. Artinya di luar kemampuan yang dimiliki manusia ada supra kekuatan yang lebih. Supra kekuatan ini dikemas manusia dalam berbagai konsep semisal kekuatan ghaib, dewa, Tuhan, Supreme Being, Dzat yang absolute, Infinite dan seterusnya.
Bangsa mesir kuno punya keyakinan terhadap dewa Osis, Osiris, dewa Ra dan mereka melakukan ritual-ritual pemujaan terhadap para dewa. Bangsa Akadia dengan kota Babilonianya yang terkenal memuja kebesaran para dewa. Bangsa Minoa yang tinggal di kepulauan Aegea dengan pusat pemerintahannya di pulau Kreta meyakini dewa Cronos sebagai kepala para dewa, dan setelah mereka dikalahkan oleh sekelompok orang yang ditenggarai berbahasa Yunani, maka mitos dewa Cronos dilenyapkan dan diganti oleh Dewa Zeus sebagai pemimpin para dewa. Menurut mitos yang dibuat oleh bangsa Yunani kuno, Dewa Cronos ini dikalahkan oleh dewa Zeus dalam peperangan, lalu dewa Cronos pun di buang ke dalam neraka tua. Bangsa Romawi memuja kebesaran dewa Jupiter, Mars dan Neptuno. Di samping ini, kita juga mengenal agama-agama lain yang ada di dunia ini yang sampai sekerang tetap eksis ditenggarai memiliki pengikut yang jumlahnya tidak sedikit, seperti Hindu, Budha, Konghucu, Sinto dengan memajukan konsep ketuhanan mereka masing-masing. Agama Hindu Bali mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan Sang Hyang Widi Wasya, hanya ada satu Tuhan dan tidak ada duanya. Pemeluk Agama Budha percaya bahwa sang Budha meyakini ada kekuatan ghaib yang maha dahsyat yang menguasai alam semesta ini. Keyakinan Konghucu mengajarkan bahwa Tuhan yang Esa adalah Thian yang memiliki empat sebutan yaitu; Tuhan yang maha besar (Thian), Pengatur Dunia (Tee atau Siang Tee), Yang Esa sebagai Penguasa (Thai Let), dan Tuhan sebagai penguasa spirit yen (Kwi Sten).
Uraian ringkas di atas baik dalam bahasa filsafat atau dengan konsep agama membuktikan bahwa secara fitrah manusia memiliki kecenderungan bathin yang kuat untuk beragama dan kecenderungan ini tidak akan musnah meskipun manusia telah mencapai peradaban modern serba tkenologi dan bahkan mendapat dukungan dari doktrin filsafat Post Positivisme. Inilah fitrah manusia dan demikianlah perjalanan manusia dalam meyakini, mencari, atau menjelaskan adanya kekuatan ghaib di balik alam semesta ini dengan konsep dan pendekatan masing-masing.
Di atas kenyataan inilah, Al Quran mewartakan kepada umat manusia, pertama, mengenai fitrah dasar manusia itu telah memberikan kesaksian adanya Tuhan, kedua, Ia jega mewartakan bahwa ada utusan dariNya yang member petunjuk mengenai hakekat wujud ghaib yang berada di balik alam semesta ini. Kata Edward Mortimer dengan pendekatan spekulatif historic, ada campur tangan Tuhan terhadap sejarah manusia dalam bentuk pengutusan para Nabi dan Rasul kepada manusia. Dan yang terjadi setelah itu adalah apakah manusia menerima atau membangkang Al Quran sebagai wahyu Tuhan yang pada zaman mula jadi telah disaksikan keberadaanNya oleh manusia menginformasikan tentang “Dia” (huwa) yang ghaib itu. Ini disebut dalam ayat pertama surat al Ikhlas “Qul Huwa Allah ahad”. Katakanlah (wahai Muhammad, seorang utusanNya yang dipilih untuk menyampaikan petunjuk kepada sesame manusia) bahwa “Dia” (huwa) adalah Allah yang esa. Ayat ini menurut pandangan Prof. Mukti Ali, lebih bermaksud memperoklamasikan nama Dzat Ghaib di balik alam ini, yakni Allah, dan bukan memproklamirkan faham monoteisme, sebab selain agama samawi (Islam) terdapat konsep monoteisme. Karena itu surat ini dinamai dengan Al-Ikhlas, dan tidak dinamai dengan surat Tawhid. Seolah surat ini mengimbau agar manusia ikhlas menerima berita dari Al Quran mengenai siapa sesungguhnya Dia, Dzat Ghaib yang berada di balik alam semesta ini.
Penulis akan sedikit meninggung istilah Nabi dan Rasul. Kata “Nabi” berasal dari kata “naba’” (tanda ‘ di akhir kata sebagai pengganti huruf “hamzah”). Naba’ artinya berita, sedangkan nabu’ berarti tempat yang tinggi. Dua makna dasar ini membeikan pengertian bahwa Nabi adalah seorang yang menerima berita dari tempat yang tinggi, dan memiliki hujjah yang tinggi sehingga mampu mengatasi hujjah-hujjah lain yang dihadapkan kepadanya. Nabi berkonotasi pada hubungan seseorang dengan Tuhan secara langsung tanpa perantara manusia lainnya, atau melalui para malaikat-Nya. Sedangkan kata Rasul berarti orang yang diutus (mursal) membawa risalah atau misi yang diberikan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada sesama manusia. Jadi konotasi makna Rasul adalah nisbah hubungan antara sesama manusia karena risalah yang dibawanya diarahkan dan ditujukan kepada sesama manusia.
3. Pembawa Tugas Syahadah : Nabi dan Rasul
Kita semua mafhum bahwa membaca syahadah dengan lafal “Asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasul Allah” menjadi rukun pertama agama Islam. Ini artinya ada kemungkinan terjadinya syahadh (penyaksian) manusia kepada dzat Tuhan Allah di dunia ini sebagaimana telah terjadi penyaksian manusia kepada Dzat Tuhan di alam dzar. Sebab kata “syahidna” dalam ayat Al Quran diatas dengan kata “Ashadu” dalam lafal syahadah sebagai rukun Islam berasal dari akar kata yang sama, “Syuhud” yang punya arti “menyaksikan” atau “bersaksi”.
Di dalam logika al-Ghazali yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 dinyatakan, iman (percaya) yang didasarkan atas penyaksian sendiri lebih mantap disbanding dengan iman yang hanya didasarkan atas berita-berita dari orang lain.
Lebih lanjut Al-Ghazali membagi jenis iman lengkap dengan penjelasannya menjadi tiga, pertama, imannya orang-orang awam yang hanya didasarkan atas berita-berita dari orang lain. Kedua imannya kaum mutakallimin yang melengkapi imannya dengan beragam dalil, dan ketiga imannya kaum ‘arifun billah’ yang didasarkan atas syahadah dengan penuh keyakinan. Melalui logika analogis ia memperlengkapi penjelasan tentang tingkat-tingkat keyakinan dengan mengajukan satu contoh konkrit tentang keyakinan bahwa “Zaid ada di dalam rumah”.
Pertama, kamu mendapat informasi dari pembantunya yang selama ini dikenal jujur dan tidak berbohong. Ia mengatakan kepadamu bahwa tuan Zaid ada di dalam rumah. Mendengar berita dari pembantu tersebut kamu meyakininya meskipun kamu tidak mendengar sendiri tuan Zaid. Inilah perumpamaan imanya orang-orang awam yang hanya didasarkan berita yang mereka peroleh dari bapak ibu mereka bahwa Allah itu wujud, punya sifat-sifat dan af’al dan mereka tidak meragukan pemberitaan dari ibu bapak mereka. Iman semacam ini bisa membawa mereka memperoleh kebahagiaan di akhirat, akan tetapi mereka tidak masuk golongan orang-orang yang muqarrabin (mungkin yang dimaksud Al Ghazali adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan) karena cahaya keyakinan tidak menembus ke dalam hati mereka. Dan kemungkinan jatuh ke dalam kesalahan sangat terbuka bagi mereka.
Tingkat kedua, kamu mendengar sendiri ucapan tuan Zaid akan tetapi posisimu berada di balik tembok rumahnya (kamu tidak menyaksikan tuan zaid dengan mata kepalamu). Dari mendengar ucapan Tuan Zaid inilah kamu berdalil bahwa tuan Zaid di dalam rumah. Dan iman dalam tingkatan ini lebih kuat dibanding iman yang hanya didasarkan atas pemberitaan orang lain.
Tingkat letiga, kamu masuk sendiri ke dalam rumah tuan Zaid dan kamu melihat dan menyaksikan tuan Zaid dengan mata kepalamu. Inilah hakekat ma’rifat dan musyahadah yang sangat meyakinkan setaraf dengan ma’rifatnya orang-orang muqorobin dan para shidiqin di mana mereka beriman atas dasar penyaksian (syahadah). Inilah tingkat kualitas iman yang lebih kuat disbanding kedua tingkat sebelumnya.
Hamka membuat ilustrasi iman orang-orang awam yang oleh al Ghazali dikatakan sebagai mudah jatuh kepada kesalahan. Dalam ilustrasinya, Hamkan menampilkan contoh orang awam dari desa yang oleh suatu dorongan tertentu pindah ke perkotaan. Orang ini sewaktu tinggal di desanya dikenal sebagai orang yang rajin menjalankan ubudiah agama. Dan kini setelah di kota, ia harus menghadapi sejumlah tantangan seperti kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak mudah, kerasnya persaingan hidup, benturan emosi, benturan kepentingan, keinginan, nafsu, kemewahan kita, akan menjadi hadangan yang boleh jadi membelokkan iman awam mengikuti kecenderungan hidup memburu kebutuhan dan kepentingan duniawiyah. Gejala awalnya bisa jadi ketika datang waktu shalat zhuhur ia tidak segera mengerjakan shalat sebagaimana masih tinggal di desa. Dari gejala sederhana ini berlanjut sampai dengan berani meninggalkan shalat karena tuntutan pekerjaan dan kebutuhan yang jika tidak ia kejar, kesempatan itu akan hilang dan sulit ditemukan kembali kesempatan semacam itu. Boleh jadi karena pergaulan ia mulai berani minum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obat terlarang dengan alas an solidaritas kawan atau desakan kawan padahal selama tidak pernah ia lakukan di desa.
Tingkat kedua, adalah imannya kaum mutakallimin, atau ulama yang menggeluti ilmu kalam, yang menurutnya tingkat ini lebih dekat kepada tingkat iman orang-orang awam. Sebagai seorang tokoh dalam ilmu kalam aliran Asy’ariyah, tentu otokrikik terhadap disiplin yang digelutinya selama ini patut memperoleh perhatian sejenak. Dalam karyanya yang lain “al-Munqidz min al-Dhalal”, beliau juga menyampaikan kritik atas disiplin ini. Katanya, ilmu kalam memang bisa memenuhi tujuannya sendiri, akan tetapi ia tidak bisa memenuhi tujuan saya.
Adapun tujuan ilmu kalam adalah menjaga akidah ahlus-sunnah dari tercampur dengan faham bid’ah yang menyesatkan. Sebagai salah seorang pengikut aliran Asy’ariyah bahkan beliau dipandang sebagai tokoh pembela aliran ini yang paling berpengaruh, beliau mengakui ada sebagian kelompok yang tenggelam dan jatuh ke dalam pusaran perselisihan, mengabaikan argumentasi pihak lain. Dan keadaan ini oleh belaiau dianggap sebagai tidak member manfaat bagi orang yang tidak mau menerima selain bukti yang memberi kepastian (dharuri). Dan bukti semacam ini tidak diperoleh melalui dalil-dalil aqli maupun nakli dalam masalah iman dank arena itulah beliau masuk ke dalam kamar tasawuf guna memperoleh iman yang didasarkan atas penyaksian dan, menurutnya, iman semacam ini merupakan tingkat iman yang paling kuat disbanding dua yang pertama. Menurut Muhammad Iqbal, salah seorang pemikir modern, disiplin ilmu kalam sebagaimana diperlihatkan oleh Mu’tazillah hanyalah bermain-main dalam logika padahal kehidupan beragama tidak hanya terbatas pada bermain-main rasio untuk kepentingan pemahaman dan kognisi melainkan menuntut adanya totalitas manusia dalam beribadah.
Kita kembali kepada pembahasan mengenai penyaksian. Penyaksian (syahadah) adalah gambaran situasi di mana terjadi hubungan langsung antara manusia sebagai subyek yang menyaksikan dengan obyek yang disaksikan. Melalui penyaksian ini terjadilah pengalaman langsung yang membuat keyakinan orang tersebut mencapai tingkat haqqul yaqien karena didasarkan atas penyaksian sendiri, dan tidak hanya didasarkan atas ucapan-ucapan atau informasi orang lain. Inilah tingkat iman orang-orang muqorobin dan shiddiqien, dan dalam kelompok ini, tentu para nabi dan rasul menjadi penghuni pertama
Sebab para nabi orang yang secara langsung menerima wahyu dari Tuhan dan diantara mereka diutus menjadi Rasul untuk menyampaikan risalahNya kepada sesame manusia.
Demikian Al Ghazali membicarakan kekhasan ilmu yang ada pada Nabi, yakni ilmu yang berada di luar jangkauan panca indera akal. Beliau menyebut dengan ilmu hakekat, ilmu yang masuk ke dalam rasa (dzauq) yang dengannya seseorang bisa merasakan lezatnya merasakan ma’rifat billah. Rasa itu semacam penyaksian (dalam teks al-Ghazali, aldzauq kal musyahadah), atau dalam rumusan Syuhrawardi al Maqtul dinyatakan secara eksplisit, “man lam yadzuq lam ya’rif” artinya “barang siapa yang tidak merasa maka ia tidak mengenal atau tidak tahu”. Ini berarti di dalam rasa itu ada pengenalan dan pengetahuan. Kalau kita minum the dan menyatakan “teh ini manis”, sebenarnya yang menyatakan ini adalah rasa. Kita tahu teh ini manis melalui rasa. Demikian pula jika kita makan garam lalu menyatakan “asin” maka rasalah sebenarnya yang menyatakannya setelah rasa ini mengadakan kontak langsung dengan garam, lalu mengerti serta mengenal rasa garam, lalu membuat putusan bahwa garam itu asin. Inilah yang dikehandaki Al Ghazali sebagai pembuktian yang dharuri, pembuktian secara langsung melalui rasa. Sebuah pembuktian yang mencapai tingkat haqqul yaqien, pembuktian yang haqiqi melebihi pembuktian yang didasarkan atas penglihatan atau pengamatan (observasi), atau pembuktian yang didasarkan atas konstruk awal, atau argument-argument rasio.
Contoh ilmuan fisika-kimia punya konstruk teori yang kita kenal dengan “atom”. Konstruk teori ini merupakan simpulan setelah melalui kajian yang mendalam dan melibatkan banyak ilmuwan dalam disiplin atom, lalu disepakati bahwa atom itu terdiri dari electron (unsure negative) dan neutron serta proton (inti atom). Electron-elektron itu diyakini bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi. Fakta atau kenyataan mengenai bagaimana electron-elektron itu bergerak cepat memang tidak dapat dilihat mata ataupun dengan bantuan alat teknologi, namun ada bukti yang menguatkan konstruk ini, missal, ketika kita menekan tombol listrik, lampu-lampu menyala, setrika berfungsi dan lain-lain. Mata kita tidak melihat electron-elektron itu bergerak pada kabel listrik mengelilingi inti atom, namun rasio kita mengabsahkan kebenaran adanya atom. Pembuktian jenis ini kit kelompokkan sebagai bukti dalam tingkat ‘ainul yaqin’ dan ‘ilmul yaqin’ (mata kita melihat bukti dan rasio kita mendeskripsikan). Namun jika kita ingin memperoleh pembuktian lebih kuat lagi, pembuktian yang mencapai haqqul yaqin, coba pegang saja kabel listrik itu dan kita akan merasakan sengatan listrik itu.
Penulis ingin menyederhanakan contoh dengan “batu”. Ketika mata kita melihat sebongkah batu, akal kita mengatakan dan percaya bahwa batu itu keras dan lebih keras dari kepala kita. Dan buktinya, ketika kita ingin tiba-tiba melihat seorang yang kepalanya tertimpa batu, ternyata kepala orang tersebut menjadi benjol-benjol. Disini kita memproleh pembuktian tingkat ‘ainul yaqin dan ‘ilmul yaqin, jika kita masih menginginkan pembuktian yang lebih kuat lagi dari dua pembuktian di atas, yakni pembuktian yang mencapai haqqul yaqin, pembuktian rasa, kita sendiri mencoba membenturkan kepala kita terhadap batu dan kita akan merasakan secara langsung betapa kerasnya batu itu.
Dari berita-berita yang disampaikan kepada orang lain kepada anda atau mungkin dari penglihatan anda sendiri lewat teve atau dari jarak jauh, anda melihat betapa indahnya dan bahagianya orang-orang yang dekat dengan Raja, hadir di depan Raja, dan berkenalan dengan sang Raja, sedang anda sendiri tidak memiliki pengalaman ini sehingga anda tidak bisa merasakan betapa indah dan bahagianya dekat dengan Raja. Dari penglihatan mata dan dari deskripsi rasio anda, anda percaya bahwa mereka yang bisa mendekat dan hadir di hadapan sang Raja merasa bahagia, sebab tidak semua orang bisa memperoleh kesempatan semacam itu, dekat, hadir, berkenalan dan berhadapan dengan orang besar, yakni Sang Raja. Dan secara psikologis, seseorang akan bangga jika ia bisa berkenalan dengan orang-orang besar yang baik budi, ramah tamah dan memiliki kekuasaan yang besar. Bahkan di dalam keseharian kita, tidak jarang kita sendiri atau kenalan-kenalan kita membanggakan diri karena pernah berkenalan dengan orang-orang besar yang baik budi dan memiliki kekuasaan yang luas, apakah orang-orang besar itu politikus, ekonom, ilmuan dst, meskipun sangat mungkin berbohong.
Anda akan merasa bangga dan bahagia yang meliputi seluruh psikis anda dan akan mengingat-ingat terus perisiwa berkenalan ini (dalam bahasa Arab, mengingat-ingat ini disebut dengan Dzikir. Dalam wacan tasawuf, orang yang mengenal Dzat Allah karena diperkenalkan oleh orang-orang yang ahlinya dalam hal ini, lalu ia diminta agar di dalam rasa hatinya selalu mengingat-ingatNya dinamakan al Dzikr).
Di dalam pengenalan atau penyaksian jenis ini yang terjadi adalah adanya hubungan langsung anda dengan yang disaksikan dan situasi ini memunculkan rasa bahagia melebihi pengalam-pengalaman lainnya yang pernah anda miliki. Kini, anda tidak hanya sekedar melihat orang lain dekat dengan sang penguasa, melainkan anda sendiri memiliki pengalaman langsung dan karena itu anda kini merasakan sendiri betapa indah dan bahagianya dekat, hadir di hadapan penguasa dan berkenalan dengannya. Alangkah indahnya jika sang Raja itu adalah Rajanya raja, atau Maha Raja, dan Dialah Allah yang menyebut diriNya adalah “Malikal Mulki”.
Inilah pembuktian tingkat rasa. Pembuktian diri secara langsung, di mana rasa yang terdapat di dalam hati anda akan merasakan langsung kehadiran Dzat Tuhan, dan melalui kehadiran ini anda akan mengenal (ma’rifat) kepada Allah. Allah di sini bukan Allah sebagai nama yang dideskripsikan oleh dalil akli atau nakli, akan tetapi Allah sebagai Dzat yang keberadaan DiriNya yang Ghaib itu sebenarnya bisa dikenal oleh rasa hatinya (sir atau dzauq, dalam konsep tasawuf).
Karena inilah muncul konsep dzikir khafi atau dzikir sirri; khaffi berarti tersembunyi sehingga orang lainpun tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang berdzikir karena dzikir itu bertempat di dalam rasa hati (sirr) sehingga orang lain yang duduk dekat dengannyapun tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang berdzikir dan dzikir yang mencapai tingkat rasa ini tidak mengganggu profesi atau pekerjaan. Misalnya, anda punya dzikir jenis ini karena melalui seorang Guru yang ahlinya, anda bisa mengamalkan dzikir ini sekaligus anda sambil anda menyelesaikan pekeraan anda sebagai guru yang tengah mengajar, atau sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian, atau sebagai staf yang sedang kerja lembur menyelesaikan laporan di depan computer dan jenis-jenis pekerjaan lain selama diperbolehkan oleh syari’at Islam. Ilmu jenis ini diperkenalkan oleh Ilmu (tasawuf) Syathariyah.
Demikianlah rasa yang memiliki pengetahuan karena di dalam dirinya bisa merasa, merasa berarti mengetahui dan mengenal. Dan rasa bahagia yang paling tinggi nilainya bagi manusia adalah ma’rifat billah (tegasnya ma’rifat bi Dzatillah) demikian Al Ghazali dalam Kimia al-Sa’adah.
Syahadah atau menyaksikan Dzat Allah yang pada alam mula jadi dahulu (alam dzarr) pernah terjadi pada diri hakiki manusia, kini, di dunia empiric ini, melalui Nabi dan RasulNya amat mungkin untuk direalisasikan. Masalah yang mungkin mengkin demikian. Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad saw sekaligus sabagai Rasul-Nya, keberadaannya di dunia ini dibatasi oleh usia. Beliau, disamping membawa ilmu syari’at, juga membawa ilmu hakekat yang isinya memperkenalkan hakekat manusia dan hakekat Allah, telah wafat mendahului kita ummat Islam yang hidup di abad 21 ini. Lalu apakah ummat sepeninggal beliau dibiarkan mencari-cari sendiri atau membuat rekayasa sendiri dalam masalah ilmu hakekat ini?. Ataukah beliau memberikan tugas ilmu hakekat ini kepada penerus yang ditunjuk oleh beliau guna membimbing umat sepeninggalnya secara berkesinambungan sampai hari kiamat?
Sebagaimana diriwayatkan, bahwa sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan khutbah di Ghadir Khum. Mukadimah dari isi khutbah ini banyak ditulis oleh para mufassir termasuk Muhammad Abduh. Dalam muqadimah khutbah ini Nabi SAW bersabda, “alastu bi awla minal mukminiina min anfusihim? Qalu, balaa” artinya, “bukankah aku (Nabi Muhammad SAW) lebih utama daripada para mukminin terhadap diri mereka sendiri?”; dan mereka menjawab, “benar”. Sabda ini diulang sampai 3 kali. Bahwa Nabi lebih utama disbanding dari kaum mukminin atas diri mereka sendiri member pengertian bahwa apa yang diputuskan atau yang dipilih oleh Nabi harus lebih diutamakan dibandingkan dari pilihan atau putusan kaum mukminin meskipun mereka bersepakat bersama memutuskan sesuatu. Dan para sahabat yang hadir mendengarkan khutbah itu merespon dengan positif. Bahwa para sahabat yang hadir pada saat itu mengakui bahwa apa-apa yang dipilih dan diputuskan Nabi lebih utama untuk dipatuhi daripada mereka sendiri, dan mereka telah menyatakan jawabannya akan mengutamakan pilihan dan putusan Nabi mereka dan sebagai mafhum mukhalfahnya, mereka akan mengabaikan pilihan atau putusan mereka sendiri meskipun mereka bersepakat bersama lewat musywarah.
Setelah mendengar respon yang demikian positif, Nabi Muhammad SAW meneruskan, “Man kuntu maulahu fa haadza ‘Alii maulaahu; allaahumma walii man waulahuu wa ‘adi man ‘adahu, allaahumma unshur man nasharahu wahdzul man khadzalahu” hatta qaala ‘Umar ibnu Khattab, “bakh, bakh, anta yaa iba ‘Abi Thalib, asbahta maulaya wamaulaa kulli mukminiina wal mukminaatin”, Artinya, “Barang siapa yang telah menjadikan aku sebagai maula-nya, maka sekarang ini ‘Ali yang akan menjadi maulanya; Allaahumma yaa Allah, kasihanilah orang yang mengasihani Ali dan musuhilah orang yang memusuhinya, tolonglah orang yang menolong ‘Ali dan hinakanlah orang yang menghinanya”. Setelah itu Ummar bin Khatab segera menyambutnya, “selamat wahai engkau putera Abi Thalib, engkau menjadi maulaku dan maula setiap orang mukmin dan mukminat.
Mawla memiliki makna pembimbing, penunjuk, teman yang penuh kasih sayang, dan Nabi menggunakan kata “mawla” ini untuk menyebut dirinya maupun untuk ‘Ali dalam kaitannya dengan umat yang akan ditinggalkan. ‘ali ditunjuk sebagai penerus rasul, demikian al-Alusi dalam tafsirnya, tidak harus berkonotasi untuk urusan politik, melainkan, menurut pandangan kaum sufi, dia ditunjuk untuk menjadi penuntun di bidang ilmu bathin, yakni ilmu hakekat, ilmu yang mempertemukan hakekat manusia dengan hakekat Tuhan Allah. Demikianlah ‘Ali menerima kenyataan dimana urusan politik dipegang oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman sebelum kemudian jatuh ke tangannya yang disusul pemberontakan Mu’awiyah. Akan tetapi dalam masalah ilmu hakekat maka itu menjadi tugasnya meneruskan tugas yang dilaksanakan oleh Nabi. Dan tugas ini pula kemudian diserahkan kepada penerusnya sebelum beliau wafat dan demikianlah penerusan tugas ini terjadi secara berkesinambungan (‘Ali kepada Hasan, kemudian kepada Husein kemudian kepada ‘Ali Zainal ‘Abidin dan seterusnya) sampai hari kiamat.
Dalam pengalaman empirik, kita juga lazim melihat terjadinya penerusan tugas kepada ahlinya. Misalnya, jika seorang guru sejarah meninggal, temntu pihak yang berwenang yang mengurusi pendidikan akan menunjuk orang lain yang ahli dalam sejarah untuk meneruskan tugas mengajar sejarah, dan tidak dibiarkan kosong tanpa guru dengan alasan sudah ada buku-buku tentang sejarah. Atau jika guru pengajar matematika meninggal, pihak yayasan pasti segera mennjuk orang yang ahli matematika untuk bertugas menggantikannya. Demikian pula jika seorang kepala desa tertentu meningal dunia, maka ia akan segera digantikan oleh orang lain dan tidak dibiarkan kosong tanpa kepala desa meskipun desa itu sudah memiliki aturan-aturan kedesaan. Logika kita mengatakan, tugas tidak ikut mati ketika pribadi yang mengemban tugas wafat. Jika dalam masalah-masalah ilmu (sejarah, matematika dll) atau dalam masalah urusan sosial politik selalu ada penerusan tugas dari pengemban tugas terdahulu kepada penerusnya, lebih-lebih dalam hal ilmu hakekat yang menjadi dasar membangun sebuah kepribadian yang normatif menurut arahan dan bimbingan maula, penerusan tugas merupakan bagian dari tuntutan ilmu hakekat itu sendiri.
Pelajaran lain tentang kehidupan yang dapat kita ambil dari Kitab Suci agama Islam, dan juga dalam agama-agama lain mapun dari beberapa faham falsafah, bahwa kehidupan manusia itu telah berlangsung semenjak sebelum alam empirik ini, dalam alam empirik ini, dan nanti setelah alam empirik ini. Mungkin kita bisa mengkonsepsikan dengan alam “pra empirik, masa empirik dan psot empirik”, atau dalam ungkapan lain yang lebih terkenal, dari alam dzar, alam dunia dan alam akherat. Sebuah garis kehidupan yang tidak terputus.
Manusia sebelum terlahir ke dunia empirik telah mengenal Tuhannya (syahadah), demikian informasi dari Al Quran. Dan kini kita mengantarkan manusia agar dapat mengenal kembali (Syahadah kepada Tuhannya) di saat hidup di alam empirik ini, Tuhan tidaklah membiarkan manusia dalam kebingungan mencari-cari Tuhannya sebagai dorongan fitrah manusia tanpa bimbingan dariNya, melainkan Dia mengutus salah satu dari hamba-hambaNya untuk tujuan mengingatkan manusia agar mengenal ulang Tuhannya sebagaimana dahulu di saat alam dzar mereka telah mengenal-Nya. Dan setelah menjalani kehidupan di alam empirik ini manusia yang bisa mengenal kembali Tuhannya melalui para RasulNya bisa bertemu lagi denganNya. Situasi bisa bertemu denganNya ini digambarkan sebagai puncak kebahagiaan manusia di kehidupan akherat nanti.
DR. Ahmad Khozin Afandi
Di samping faktor intern-fitrah, faktor-faktor eksternal turut mendorong manusia mencari kekuatan ghaib itu. Dalam hidup di atas bumi ini, manusia dihadakan dengan lingkunan alami yang seringkali tidak ramah terhadap nasib mereka seperti banjir, gempa bumi, halilintar, wabah penyakit, serangan hama, gunung meletus, dan lain-lain gangguan alam yang setiap saat dan dengan tiba-tiba mengancurkan harapan mereka. Pada sisi internal, mereka memiliki sebuah rencana, cita-cita, ambisi, kepentingan, nafsu keinginan bahkan sifat-sifat tamak, serakah, zhalim, dan sejumlah sifat-sifat lainnya yang bisa berdampak merugikan orang lain atau pihak-pihak lain.
Berkembangnya faktor internal-fitrah ini didasarkan atas fakta potensial, atau natural faculties (kemampuan alami), meminjam istilah John Locke yang menolak teori innatea idea platonis, yang dimiliki manusia. Kemampuan alami yang dimiliki manusia itu adalah panca indera dan akal rasio. Kemampuan inilah yang dipakai dan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi cita-cita, ambisi, kepentingan dan kebutuhan sehari-hari, namun ia juga bisa diasah dan dipertajam melalui pendidikan kehalian dan keterampilan untuk melakukan observasi ilmiah, merumuskan hipotesis, mengujiknya lewat eksperimen, guna melahirkan atau membuktikan kebenaran teori, atau untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan lain yang terpendam di balik alam. Hasilnya adalah peradaban modern sebagaimana kita saksikan ini lengkap dengan segala produk dan temuan teknologi di sektor kehidupan mulai dari bumbu masak sampai ruang angkasa.
Keadaan inilah yang dikonsepsikan oleh Auguste Comte sebagai tahap positive atau tahap ilmiah di mana simpulan empirik dan kalkulasi rasio memainkan peranan penting sekaligus menyingkirkan cara berfikir tahap teologis dan tahap metafisik dari percaturan peradaban karena tidak diperlukan lagi. Boleh jadi Comte tidak pernah memperhitungkan konsekuensi praktis yang tidak jarang menyimpang dari perhitungan dan rancangan manusia. Peluncuran pesawat ruang angkasa yang sudah dirancang dengan teknologi tinggi tiba-tiba meledak dan hancur berkeping-keping. Tiba-tiba terjadi kebocoran di pabrik nuklir atau bahkan meledak dan meluluh lantakkan bangunan dan memakan korban jiwa. Tiba-tiba terjadi angin puting beliung yang melumatkan bangunan yang super canggih dan tidak mampu dikendalikan oleh teknologi manusia. Tiba-tiba terjadi gempa bumi atau gunung meletus dengan kekuatan yang dahsyat memakan habis bangunan dan menelan manusia. Atau bahkan tangan-tangan manusia itu sendiri yang membuat kerusakan secara langsung. Tiba-tiba terjadi kontak senjata, terjadi peperangan, terjadi permusuhan manusia oleh manusia, terjadi amuk masa, terjadi pembunuhan secara masal atas nama doktrin kiamat dalam suatu sekte tertentu dan masih banyak kasus-kasus lain yang tak mungkin diturunkan di sini semuanya. Memang harus diakui bahwa manusia dengan kemampuan akal, teori dan teknologi yang dikuasainya bias membuat rancangan ke depan, akan tetapi tetap saja berlaku premis dasar yang menyatakan bahwa masa depan adalah ibarat sebuah gudang yang menyimpan seribu ketidakpastian. Dalam kemasan agama, ungkapan bijak itu menyatakan manusia berusaha, namun Tuhanlah juga yang menentukan. Artinya di luar kemampuan yang dimiliki manusia ada supra kekuatan yang lebih. Supra kekuatan ini dikemas manusia dalam berbagai konsep semisal kekuatan ghaib, dewa, Tuhan, Supreme Being, Dzat yang absolute, Infinite dan seterusnya.
Bangsa mesir kuno punya keyakinan terhadap dewa Osis, Osiris, dewa Ra dan mereka melakukan ritual-ritual pemujaan terhadap para dewa. Bangsa Akadia dengan kota Babilonianya yang terkenal memuja kebesaran para dewa. Bangsa Minoa yang tinggal di kepulauan Aegea dengan pusat pemerintahannya di pulau Kreta meyakini dewa Cronos sebagai kepala para dewa, dan setelah mereka dikalahkan oleh sekelompok orang yang ditenggarai berbahasa Yunani, maka mitos dewa Cronos dilenyapkan dan diganti oleh Dewa Zeus sebagai pemimpin para dewa. Menurut mitos yang dibuat oleh bangsa Yunani kuno, Dewa Cronos ini dikalahkan oleh dewa Zeus dalam peperangan, lalu dewa Cronos pun di buang ke dalam neraka tua. Bangsa Romawi memuja kebesaran dewa Jupiter, Mars dan Neptuno. Di samping ini, kita juga mengenal agama-agama lain yang ada di dunia ini yang sampai sekerang tetap eksis ditenggarai memiliki pengikut yang jumlahnya tidak sedikit, seperti Hindu, Budha, Konghucu, Sinto dengan memajukan konsep ketuhanan mereka masing-masing. Agama Hindu Bali mempercayai Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan Sang Hyang Widi Wasya, hanya ada satu Tuhan dan tidak ada duanya. Pemeluk Agama Budha percaya bahwa sang Budha meyakini ada kekuatan ghaib yang maha dahsyat yang menguasai alam semesta ini. Keyakinan Konghucu mengajarkan bahwa Tuhan yang Esa adalah Thian yang memiliki empat sebutan yaitu; Tuhan yang maha besar (Thian), Pengatur Dunia (Tee atau Siang Tee), Yang Esa sebagai Penguasa (Thai Let), dan Tuhan sebagai penguasa spirit yen (Kwi Sten).
Uraian ringkas di atas baik dalam bahasa filsafat atau dengan konsep agama membuktikan bahwa secara fitrah manusia memiliki kecenderungan bathin yang kuat untuk beragama dan kecenderungan ini tidak akan musnah meskipun manusia telah mencapai peradaban modern serba tkenologi dan bahkan mendapat dukungan dari doktrin filsafat Post Positivisme. Inilah fitrah manusia dan demikianlah perjalanan manusia dalam meyakini, mencari, atau menjelaskan adanya kekuatan ghaib di balik alam semesta ini dengan konsep dan pendekatan masing-masing.
Di atas kenyataan inilah, Al Quran mewartakan kepada umat manusia, pertama, mengenai fitrah dasar manusia itu telah memberikan kesaksian adanya Tuhan, kedua, Ia jega mewartakan bahwa ada utusan dariNya yang member petunjuk mengenai hakekat wujud ghaib yang berada di balik alam semesta ini. Kata Edward Mortimer dengan pendekatan spekulatif historic, ada campur tangan Tuhan terhadap sejarah manusia dalam bentuk pengutusan para Nabi dan Rasul kepada manusia. Dan yang terjadi setelah itu adalah apakah manusia menerima atau membangkang Al Quran sebagai wahyu Tuhan yang pada zaman mula jadi telah disaksikan keberadaanNya oleh manusia menginformasikan tentang “Dia” (huwa) yang ghaib itu. Ini disebut dalam ayat pertama surat al Ikhlas “Qul Huwa Allah ahad”. Katakanlah (wahai Muhammad, seorang utusanNya yang dipilih untuk menyampaikan petunjuk kepada sesame manusia) bahwa “Dia” (huwa) adalah Allah yang esa. Ayat ini menurut pandangan Prof. Mukti Ali, lebih bermaksud memperoklamasikan nama Dzat Ghaib di balik alam ini, yakni Allah, dan bukan memproklamirkan faham monoteisme, sebab selain agama samawi (Islam) terdapat konsep monoteisme. Karena itu surat ini dinamai dengan Al-Ikhlas, dan tidak dinamai dengan surat Tawhid. Seolah surat ini mengimbau agar manusia ikhlas menerima berita dari Al Quran mengenai siapa sesungguhnya Dia, Dzat Ghaib yang berada di balik alam semesta ini.
Penulis akan sedikit meninggung istilah Nabi dan Rasul. Kata “Nabi” berasal dari kata “naba’” (tanda ‘ di akhir kata sebagai pengganti huruf “hamzah”). Naba’ artinya berita, sedangkan nabu’ berarti tempat yang tinggi. Dua makna dasar ini membeikan pengertian bahwa Nabi adalah seorang yang menerima berita dari tempat yang tinggi, dan memiliki hujjah yang tinggi sehingga mampu mengatasi hujjah-hujjah lain yang dihadapkan kepadanya. Nabi berkonotasi pada hubungan seseorang dengan Tuhan secara langsung tanpa perantara manusia lainnya, atau melalui para malaikat-Nya. Sedangkan kata Rasul berarti orang yang diutus (mursal) membawa risalah atau misi yang diberikan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada sesama manusia. Jadi konotasi makna Rasul adalah nisbah hubungan antara sesama manusia karena risalah yang dibawanya diarahkan dan ditujukan kepada sesama manusia.
3. Pembawa Tugas Syahadah : Nabi dan Rasul
Kita semua mafhum bahwa membaca syahadah dengan lafal “Asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasul Allah” menjadi rukun pertama agama Islam. Ini artinya ada kemungkinan terjadinya syahadh (penyaksian) manusia kepada dzat Tuhan Allah di dunia ini sebagaimana telah terjadi penyaksian manusia kepada Dzat Tuhan di alam dzar. Sebab kata “syahidna” dalam ayat Al Quran diatas dengan kata “Ashadu” dalam lafal syahadah sebagai rukun Islam berasal dari akar kata yang sama, “Syuhud” yang punya arti “menyaksikan” atau “bersaksi”.
Di dalam logika al-Ghazali yang ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 dinyatakan, iman (percaya) yang didasarkan atas penyaksian sendiri lebih mantap disbanding dengan iman yang hanya didasarkan atas berita-berita dari orang lain.
Lebih lanjut Al-Ghazali membagi jenis iman lengkap dengan penjelasannya menjadi tiga, pertama, imannya orang-orang awam yang hanya didasarkan atas berita-berita dari orang lain. Kedua imannya kaum mutakallimin yang melengkapi imannya dengan beragam dalil, dan ketiga imannya kaum ‘arifun billah’ yang didasarkan atas syahadah dengan penuh keyakinan. Melalui logika analogis ia memperlengkapi penjelasan tentang tingkat-tingkat keyakinan dengan mengajukan satu contoh konkrit tentang keyakinan bahwa “Zaid ada di dalam rumah”.
Pertama, kamu mendapat informasi dari pembantunya yang selama ini dikenal jujur dan tidak berbohong. Ia mengatakan kepadamu bahwa tuan Zaid ada di dalam rumah. Mendengar berita dari pembantu tersebut kamu meyakininya meskipun kamu tidak mendengar sendiri tuan Zaid. Inilah perumpamaan imanya orang-orang awam yang hanya didasarkan berita yang mereka peroleh dari bapak ibu mereka bahwa Allah itu wujud, punya sifat-sifat dan af’al dan mereka tidak meragukan pemberitaan dari ibu bapak mereka. Iman semacam ini bisa membawa mereka memperoleh kebahagiaan di akhirat, akan tetapi mereka tidak masuk golongan orang-orang yang muqarrabin (mungkin yang dimaksud Al Ghazali adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan) karena cahaya keyakinan tidak menembus ke dalam hati mereka. Dan kemungkinan jatuh ke dalam kesalahan sangat terbuka bagi mereka.
Tingkat kedua, kamu mendengar sendiri ucapan tuan Zaid akan tetapi posisimu berada di balik tembok rumahnya (kamu tidak menyaksikan tuan zaid dengan mata kepalamu). Dari mendengar ucapan Tuan Zaid inilah kamu berdalil bahwa tuan Zaid di dalam rumah. Dan iman dalam tingkatan ini lebih kuat dibanding iman yang hanya didasarkan atas pemberitaan orang lain.
Tingkat letiga, kamu masuk sendiri ke dalam rumah tuan Zaid dan kamu melihat dan menyaksikan tuan Zaid dengan mata kepalamu. Inilah hakekat ma’rifat dan musyahadah yang sangat meyakinkan setaraf dengan ma’rifatnya orang-orang muqorobin dan para shidiqin di mana mereka beriman atas dasar penyaksian (syahadah). Inilah tingkat kualitas iman yang lebih kuat disbanding kedua tingkat sebelumnya.
Hamka membuat ilustrasi iman orang-orang awam yang oleh al Ghazali dikatakan sebagai mudah jatuh kepada kesalahan. Dalam ilustrasinya, Hamkan menampilkan contoh orang awam dari desa yang oleh suatu dorongan tertentu pindah ke perkotaan. Orang ini sewaktu tinggal di desanya dikenal sebagai orang yang rajin menjalankan ubudiah agama. Dan kini setelah di kota, ia harus menghadapi sejumlah tantangan seperti kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak mudah, kerasnya persaingan hidup, benturan emosi, benturan kepentingan, keinginan, nafsu, kemewahan kita, akan menjadi hadangan yang boleh jadi membelokkan iman awam mengikuti kecenderungan hidup memburu kebutuhan dan kepentingan duniawiyah. Gejala awalnya bisa jadi ketika datang waktu shalat zhuhur ia tidak segera mengerjakan shalat sebagaimana masih tinggal di desa. Dari gejala sederhana ini berlanjut sampai dengan berani meninggalkan shalat karena tuntutan pekerjaan dan kebutuhan yang jika tidak ia kejar, kesempatan itu akan hilang dan sulit ditemukan kembali kesempatan semacam itu. Boleh jadi karena pergaulan ia mulai berani minum minuman keras atau mengkonsumsi obat-obat terlarang dengan alas an solidaritas kawan atau desakan kawan padahal selama tidak pernah ia lakukan di desa.
Tingkat kedua, adalah imannya kaum mutakallimin, atau ulama yang menggeluti ilmu kalam, yang menurutnya tingkat ini lebih dekat kepada tingkat iman orang-orang awam. Sebagai seorang tokoh dalam ilmu kalam aliran Asy’ariyah, tentu otokrikik terhadap disiplin yang digelutinya selama ini patut memperoleh perhatian sejenak. Dalam karyanya yang lain “al-Munqidz min al-Dhalal”, beliau juga menyampaikan kritik atas disiplin ini. Katanya, ilmu kalam memang bisa memenuhi tujuannya sendiri, akan tetapi ia tidak bisa memenuhi tujuan saya.
Adapun tujuan ilmu kalam adalah menjaga akidah ahlus-sunnah dari tercampur dengan faham bid’ah yang menyesatkan. Sebagai salah seorang pengikut aliran Asy’ariyah bahkan beliau dipandang sebagai tokoh pembela aliran ini yang paling berpengaruh, beliau mengakui ada sebagian kelompok yang tenggelam dan jatuh ke dalam pusaran perselisihan, mengabaikan argumentasi pihak lain. Dan keadaan ini oleh belaiau dianggap sebagai tidak member manfaat bagi orang yang tidak mau menerima selain bukti yang memberi kepastian (dharuri). Dan bukti semacam ini tidak diperoleh melalui dalil-dalil aqli maupun nakli dalam masalah iman dank arena itulah beliau masuk ke dalam kamar tasawuf guna memperoleh iman yang didasarkan atas penyaksian dan, menurutnya, iman semacam ini merupakan tingkat iman yang paling kuat disbanding dua yang pertama. Menurut Muhammad Iqbal, salah seorang pemikir modern, disiplin ilmu kalam sebagaimana diperlihatkan oleh Mu’tazillah hanyalah bermain-main dalam logika padahal kehidupan beragama tidak hanya terbatas pada bermain-main rasio untuk kepentingan pemahaman dan kognisi melainkan menuntut adanya totalitas manusia dalam beribadah.
Kita kembali kepada pembahasan mengenai penyaksian. Penyaksian (syahadah) adalah gambaran situasi di mana terjadi hubungan langsung antara manusia sebagai subyek yang menyaksikan dengan obyek yang disaksikan. Melalui penyaksian ini terjadilah pengalaman langsung yang membuat keyakinan orang tersebut mencapai tingkat haqqul yaqien karena didasarkan atas penyaksian sendiri, dan tidak hanya didasarkan atas ucapan-ucapan atau informasi orang lain. Inilah tingkat iman orang-orang muqorobin dan shiddiqien, dan dalam kelompok ini, tentu para nabi dan rasul menjadi penghuni pertama
Sebab para nabi orang yang secara langsung menerima wahyu dari Tuhan dan diantara mereka diutus menjadi Rasul untuk menyampaikan risalahNya kepada sesame manusia.
Demikian Al Ghazali membicarakan kekhasan ilmu yang ada pada Nabi, yakni ilmu yang berada di luar jangkauan panca indera akal. Beliau menyebut dengan ilmu hakekat, ilmu yang masuk ke dalam rasa (dzauq) yang dengannya seseorang bisa merasakan lezatnya merasakan ma’rifat billah. Rasa itu semacam penyaksian (dalam teks al-Ghazali, aldzauq kal musyahadah), atau dalam rumusan Syuhrawardi al Maqtul dinyatakan secara eksplisit, “man lam yadzuq lam ya’rif” artinya “barang siapa yang tidak merasa maka ia tidak mengenal atau tidak tahu”. Ini berarti di dalam rasa itu ada pengenalan dan pengetahuan. Kalau kita minum the dan menyatakan “teh ini manis”, sebenarnya yang menyatakan ini adalah rasa. Kita tahu teh ini manis melalui rasa. Demikian pula jika kita makan garam lalu menyatakan “asin” maka rasalah sebenarnya yang menyatakannya setelah rasa ini mengadakan kontak langsung dengan garam, lalu mengerti serta mengenal rasa garam, lalu membuat putusan bahwa garam itu asin. Inilah yang dikehandaki Al Ghazali sebagai pembuktian yang dharuri, pembuktian secara langsung melalui rasa. Sebuah pembuktian yang mencapai tingkat haqqul yaqien, pembuktian yang haqiqi melebihi pembuktian yang didasarkan atas penglihatan atau pengamatan (observasi), atau pembuktian yang didasarkan atas konstruk awal, atau argument-argument rasio.
Contoh ilmuan fisika-kimia punya konstruk teori yang kita kenal dengan “atom”. Konstruk teori ini merupakan simpulan setelah melalui kajian yang mendalam dan melibatkan banyak ilmuwan dalam disiplin atom, lalu disepakati bahwa atom itu terdiri dari electron (unsure negative) dan neutron serta proton (inti atom). Electron-elektron itu diyakini bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan tinggi. Fakta atau kenyataan mengenai bagaimana electron-elektron itu bergerak cepat memang tidak dapat dilihat mata ataupun dengan bantuan alat teknologi, namun ada bukti yang menguatkan konstruk ini, missal, ketika kita menekan tombol listrik, lampu-lampu menyala, setrika berfungsi dan lain-lain. Mata kita tidak melihat electron-elektron itu bergerak pada kabel listrik mengelilingi inti atom, namun rasio kita mengabsahkan kebenaran adanya atom. Pembuktian jenis ini kit kelompokkan sebagai bukti dalam tingkat ‘ainul yaqin’ dan ‘ilmul yaqin’ (mata kita melihat bukti dan rasio kita mendeskripsikan). Namun jika kita ingin memperoleh pembuktian lebih kuat lagi, pembuktian yang mencapai haqqul yaqin, coba pegang saja kabel listrik itu dan kita akan merasakan sengatan listrik itu.
Penulis ingin menyederhanakan contoh dengan “batu”. Ketika mata kita melihat sebongkah batu, akal kita mengatakan dan percaya bahwa batu itu keras dan lebih keras dari kepala kita. Dan buktinya, ketika kita ingin tiba-tiba melihat seorang yang kepalanya tertimpa batu, ternyata kepala orang tersebut menjadi benjol-benjol. Disini kita memproleh pembuktian tingkat ‘ainul yaqin dan ‘ilmul yaqin, jika kita masih menginginkan pembuktian yang lebih kuat lagi dari dua pembuktian di atas, yakni pembuktian yang mencapai haqqul yaqin, pembuktian rasa, kita sendiri mencoba membenturkan kepala kita terhadap batu dan kita akan merasakan secara langsung betapa kerasnya batu itu.
Dari berita-berita yang disampaikan kepada orang lain kepada anda atau mungkin dari penglihatan anda sendiri lewat teve atau dari jarak jauh, anda melihat betapa indahnya dan bahagianya orang-orang yang dekat dengan Raja, hadir di depan Raja, dan berkenalan dengan sang Raja, sedang anda sendiri tidak memiliki pengalaman ini sehingga anda tidak bisa merasakan betapa indah dan bahagianya dekat dengan Raja. Dari penglihatan mata dan dari deskripsi rasio anda, anda percaya bahwa mereka yang bisa mendekat dan hadir di hadapan sang Raja merasa bahagia, sebab tidak semua orang bisa memperoleh kesempatan semacam itu, dekat, hadir, berkenalan dan berhadapan dengan orang besar, yakni Sang Raja. Dan secara psikologis, seseorang akan bangga jika ia bisa berkenalan dengan orang-orang besar yang baik budi, ramah tamah dan memiliki kekuasaan yang besar. Bahkan di dalam keseharian kita, tidak jarang kita sendiri atau kenalan-kenalan kita membanggakan diri karena pernah berkenalan dengan orang-orang besar yang baik budi dan memiliki kekuasaan yang luas, apakah orang-orang besar itu politikus, ekonom, ilmuan dst, meskipun sangat mungkin berbohong.
Anda akan merasa bangga dan bahagia yang meliputi seluruh psikis anda dan akan mengingat-ingat terus perisiwa berkenalan ini (dalam bahasa Arab, mengingat-ingat ini disebut dengan Dzikir. Dalam wacan tasawuf, orang yang mengenal Dzat Allah karena diperkenalkan oleh orang-orang yang ahlinya dalam hal ini, lalu ia diminta agar di dalam rasa hatinya selalu mengingat-ingatNya dinamakan al Dzikr).
Di dalam pengenalan atau penyaksian jenis ini yang terjadi adalah adanya hubungan langsung anda dengan yang disaksikan dan situasi ini memunculkan rasa bahagia melebihi pengalam-pengalaman lainnya yang pernah anda miliki. Kini, anda tidak hanya sekedar melihat orang lain dekat dengan sang penguasa, melainkan anda sendiri memiliki pengalaman langsung dan karena itu anda kini merasakan sendiri betapa indah dan bahagianya dekat, hadir di hadapan penguasa dan berkenalan dengannya. Alangkah indahnya jika sang Raja itu adalah Rajanya raja, atau Maha Raja, dan Dialah Allah yang menyebut diriNya adalah “Malikal Mulki”.
Inilah pembuktian tingkat rasa. Pembuktian diri secara langsung, di mana rasa yang terdapat di dalam hati anda akan merasakan langsung kehadiran Dzat Tuhan, dan melalui kehadiran ini anda akan mengenal (ma’rifat) kepada Allah. Allah di sini bukan Allah sebagai nama yang dideskripsikan oleh dalil akli atau nakli, akan tetapi Allah sebagai Dzat yang keberadaan DiriNya yang Ghaib itu sebenarnya bisa dikenal oleh rasa hatinya (sir atau dzauq, dalam konsep tasawuf).
Karena inilah muncul konsep dzikir khafi atau dzikir sirri; khaffi berarti tersembunyi sehingga orang lainpun tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang berdzikir karena dzikir itu bertempat di dalam rasa hati (sirr) sehingga orang lain yang duduk dekat dengannyapun tidak mendengar dan tidak mengetahui bahwa dia sebenarnya sedang berdzikir dan dzikir yang mencapai tingkat rasa ini tidak mengganggu profesi atau pekerjaan. Misalnya, anda punya dzikir jenis ini karena melalui seorang Guru yang ahlinya, anda bisa mengamalkan dzikir ini sekaligus anda sambil anda menyelesaikan pekeraan anda sebagai guru yang tengah mengajar, atau sebagai mahasiswa yang sedang mengerjakan ujian, atau sebagai staf yang sedang kerja lembur menyelesaikan laporan di depan computer dan jenis-jenis pekerjaan lain selama diperbolehkan oleh syari’at Islam. Ilmu jenis ini diperkenalkan oleh Ilmu (tasawuf) Syathariyah.
Demikianlah rasa yang memiliki pengetahuan karena di dalam dirinya bisa merasa, merasa berarti mengetahui dan mengenal. Dan rasa bahagia yang paling tinggi nilainya bagi manusia adalah ma’rifat billah (tegasnya ma’rifat bi Dzatillah) demikian Al Ghazali dalam Kimia al-Sa’adah.
Syahadah atau menyaksikan Dzat Allah yang pada alam mula jadi dahulu (alam dzarr) pernah terjadi pada diri hakiki manusia, kini, di dunia empiric ini, melalui Nabi dan RasulNya amat mungkin untuk direalisasikan. Masalah yang mungkin mengkin demikian. Nabi terakhir yakni Nabi Muhammad saw sekaligus sabagai Rasul-Nya, keberadaannya di dunia ini dibatasi oleh usia. Beliau, disamping membawa ilmu syari’at, juga membawa ilmu hakekat yang isinya memperkenalkan hakekat manusia dan hakekat Allah, telah wafat mendahului kita ummat Islam yang hidup di abad 21 ini. Lalu apakah ummat sepeninggal beliau dibiarkan mencari-cari sendiri atau membuat rekayasa sendiri dalam masalah ilmu hakekat ini?. Ataukah beliau memberikan tugas ilmu hakekat ini kepada penerus yang ditunjuk oleh beliau guna membimbing umat sepeninggalnya secara berkesinambungan sampai hari kiamat?
Sebagaimana diriwayatkan, bahwa sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan khutbah di Ghadir Khum. Mukadimah dari isi khutbah ini banyak ditulis oleh para mufassir termasuk Muhammad Abduh. Dalam muqadimah khutbah ini Nabi SAW bersabda, “alastu bi awla minal mukminiina min anfusihim? Qalu, balaa” artinya, “bukankah aku (Nabi Muhammad SAW) lebih utama daripada para mukminin terhadap diri mereka sendiri?”; dan mereka menjawab, “benar”. Sabda ini diulang sampai 3 kali. Bahwa Nabi lebih utama disbanding dari kaum mukminin atas diri mereka sendiri member pengertian bahwa apa yang diputuskan atau yang dipilih oleh Nabi harus lebih diutamakan dibandingkan dari pilihan atau putusan kaum mukminin meskipun mereka bersepakat bersama memutuskan sesuatu. Dan para sahabat yang hadir mendengarkan khutbah itu merespon dengan positif. Bahwa para sahabat yang hadir pada saat itu mengakui bahwa apa-apa yang dipilih dan diputuskan Nabi lebih utama untuk dipatuhi daripada mereka sendiri, dan mereka telah menyatakan jawabannya akan mengutamakan pilihan dan putusan Nabi mereka dan sebagai mafhum mukhalfahnya, mereka akan mengabaikan pilihan atau putusan mereka sendiri meskipun mereka bersepakat bersama lewat musywarah.
Setelah mendengar respon yang demikian positif, Nabi Muhammad SAW meneruskan, “Man kuntu maulahu fa haadza ‘Alii maulaahu; allaahumma walii man waulahuu wa ‘adi man ‘adahu, allaahumma unshur man nasharahu wahdzul man khadzalahu” hatta qaala ‘Umar ibnu Khattab, “bakh, bakh, anta yaa iba ‘Abi Thalib, asbahta maulaya wamaulaa kulli mukminiina wal mukminaatin”, Artinya, “Barang siapa yang telah menjadikan aku sebagai maula-nya, maka sekarang ini ‘Ali yang akan menjadi maulanya; Allaahumma yaa Allah, kasihanilah orang yang mengasihani Ali dan musuhilah orang yang memusuhinya, tolonglah orang yang menolong ‘Ali dan hinakanlah orang yang menghinanya”. Setelah itu Ummar bin Khatab segera menyambutnya, “selamat wahai engkau putera Abi Thalib, engkau menjadi maulaku dan maula setiap orang mukmin dan mukminat.
Mawla memiliki makna pembimbing, penunjuk, teman yang penuh kasih sayang, dan Nabi menggunakan kata “mawla” ini untuk menyebut dirinya maupun untuk ‘Ali dalam kaitannya dengan umat yang akan ditinggalkan. ‘ali ditunjuk sebagai penerus rasul, demikian al-Alusi dalam tafsirnya, tidak harus berkonotasi untuk urusan politik, melainkan, menurut pandangan kaum sufi, dia ditunjuk untuk menjadi penuntun di bidang ilmu bathin, yakni ilmu hakekat, ilmu yang mempertemukan hakekat manusia dengan hakekat Tuhan Allah. Demikianlah ‘Ali menerima kenyataan dimana urusan politik dipegang oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman sebelum kemudian jatuh ke tangannya yang disusul pemberontakan Mu’awiyah. Akan tetapi dalam masalah ilmu hakekat maka itu menjadi tugasnya meneruskan tugas yang dilaksanakan oleh Nabi. Dan tugas ini pula kemudian diserahkan kepada penerusnya sebelum beliau wafat dan demikianlah penerusan tugas ini terjadi secara berkesinambungan (‘Ali kepada Hasan, kemudian kepada Husein kemudian kepada ‘Ali Zainal ‘Abidin dan seterusnya) sampai hari kiamat.
Dalam pengalaman empirik, kita juga lazim melihat terjadinya penerusan tugas kepada ahlinya. Misalnya, jika seorang guru sejarah meninggal, temntu pihak yang berwenang yang mengurusi pendidikan akan menunjuk orang lain yang ahli dalam sejarah untuk meneruskan tugas mengajar sejarah, dan tidak dibiarkan kosong tanpa guru dengan alasan sudah ada buku-buku tentang sejarah. Atau jika guru pengajar matematika meninggal, pihak yayasan pasti segera mennjuk orang yang ahli matematika untuk bertugas menggantikannya. Demikian pula jika seorang kepala desa tertentu meningal dunia, maka ia akan segera digantikan oleh orang lain dan tidak dibiarkan kosong tanpa kepala desa meskipun desa itu sudah memiliki aturan-aturan kedesaan. Logika kita mengatakan, tugas tidak ikut mati ketika pribadi yang mengemban tugas wafat. Jika dalam masalah-masalah ilmu (sejarah, matematika dll) atau dalam masalah urusan sosial politik selalu ada penerusan tugas dari pengemban tugas terdahulu kepada penerusnya, lebih-lebih dalam hal ilmu hakekat yang menjadi dasar membangun sebuah kepribadian yang normatif menurut arahan dan bimbingan maula, penerusan tugas merupakan bagian dari tuntutan ilmu hakekat itu sendiri.
Pelajaran lain tentang kehidupan yang dapat kita ambil dari Kitab Suci agama Islam, dan juga dalam agama-agama lain mapun dari beberapa faham falsafah, bahwa kehidupan manusia itu telah berlangsung semenjak sebelum alam empirik ini, dalam alam empirik ini, dan nanti setelah alam empirik ini. Mungkin kita bisa mengkonsepsikan dengan alam “pra empirik, masa empirik dan psot empirik”, atau dalam ungkapan lain yang lebih terkenal, dari alam dzar, alam dunia dan alam akherat. Sebuah garis kehidupan yang tidak terputus.
Manusia sebelum terlahir ke dunia empirik telah mengenal Tuhannya (syahadah), demikian informasi dari Al Quran. Dan kini kita mengantarkan manusia agar dapat mengenal kembali (Syahadah kepada Tuhannya) di saat hidup di alam empirik ini, Tuhan tidaklah membiarkan manusia dalam kebingungan mencari-cari Tuhannya sebagai dorongan fitrah manusia tanpa bimbingan dariNya, melainkan Dia mengutus salah satu dari hamba-hambaNya untuk tujuan mengingatkan manusia agar mengenal ulang Tuhannya sebagaimana dahulu di saat alam dzar mereka telah mengenal-Nya. Dan setelah menjalani kehidupan di alam empirik ini manusia yang bisa mengenal kembali Tuhannya melalui para RasulNya bisa bertemu lagi denganNya. Situasi bisa bertemu denganNya ini digambarkan sebagai puncak kebahagiaan manusia di kehidupan akherat nanti.
DR. Ahmad Khozin Afandi
Kamis, 18 Maret 2010
TENTANG SYAHADAT DARI ALAM IDE KE REALITAS EMPIRIK
TENTANG SYAHADAT DARI ALAM IDE KE REALITAS EMPIRIK
Oleh : DR. Khozin Affandi
172. dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"
Materi pokok dari ayat ini adalah mengenai kesaksian manusia akan adanya wujud Tuhan (syahadah). Akan tetapi kesaksian ini tidak terjadi di alam empirik melainkan di alam lain sebelum manusia menginjak alam empirik yaitu alam sebelum manusia dilahirkan, before born, di alam ini manusia telah mengenal ide, atau innate idea. Karena penyaksian ini terjadi di alam sebelum alam empirik, maka tidak mustahil jika manusia lupa atau tidak menyadari kejadian (penyaksian) tersbut.
Oleh sebab itu, ayat ini mengingatkan ayat keturunan Adam mengenai syahadah tersebut supaya nanti pada hari kiamat mereka tidak mencari alasan untuk mengelakkan diri. Lewat ayat ini manusia diberitahu supaya ia menjadi diri yang memiliki pengetahuan tentang syahadah. Peristiwa yang terjadi di alam praempirik ini bisa dikiaskan dengan alambayi yang baru lahir untuk memulai menjalani kehidupan di alam empirik; meskipun bayi ini sudah hidup di alam empirik, namun kesadaran mereka belum berkembang sehingga bayi itu tidak dapat mengingat apa-apa, bahkan tentang nama dirinya. Baru nanti setelah besar dia diberitahu oleh orang tuanya bahwa ia diberi nama fulan. Anehnya si anak ini percaya begitu saja bahwa ia bernama fulan.
Kita hanya mengajukan logika yang sederhana. Jika di awal alame mpirik saja seseorag tidak menyadari banyak hal yang terjadi pada dirinya ketika masih bayi, apalagi ketika ia masih di alam praempirik. Logika sederhana lainnya ialah; jika berita yang disampaikan oleh orang tentang masa bayinya bisa dipercayainya, apalagi jika verita itu disampaikanoleh Tuhan sang Penguasa Kehidupan Manusia.
Para filosof Yunani kuno, telah membahas pengetahuan manusia, apakah terjadi before born, innate (bawaan), ataukah terjadi setelah di alam empirik. Penulis menurunkan kajian filosofi tentang alamide di bawah ini tidak dimaksudkan untuk tujuan mencocokkan ayat Al Quran dengan tesa-tesa filsafat, apalagi mempersamakan tesa-tesa filsafat sejajar dengan ayat Al Quran, melainkan lebih dimaksudkan untuk membantu memperoleh pemahaman yang bersifat konstekstual. Dalam hal ini, filsafat ditempatkan sebagai sarana atau alat bantu guna mencapai sesuatu dan sesuatu yang hendak dicapai itu adalah pemahaman. Boleh jadi dengan alat bantu ini bisa menghasilkan pemahaman yang baru atau mungkin lebih mantap. Sebagai alat bantu ia bersifat hiipotetik dan ekstrinsik. Ibarat ibu-ibu yang sedang memasak di dapur yang pada saat tertentu membutuhkan pisau, sebagai alat bantu guna mempermudah pekerjaannya, tapi di saat yang lain ia tidak membutuhkan pisau karena obyek yang sedang ditangani memang tidak membutuhkan alat bantu pisau itu.
1. Tentang alam ide.
Adalah para filsof Yunani yang membuka lembaran wacana filsafat dengan mendiskusikan berbagai tema dan isu, dan salah satu tema yang tetap menjadi topik pembicaraan adalah tentang alam ide.
Plato mengkonsepsikan ide sebagai realitas yang sesungguhnya, realitas yang hakiki, sebaliknya, alam yang nampak nyata secara inderawi ini tak lain melainkan dunia bayangan dari alam ide atau alam yang hakiki. Sebagai alam yang sesungguhnya, ide itu tunggal, satu, tetap, tidak berubah dan abadi. Sebaliknya, dunia yang nampak inderawi ini bersifat berubah-uabh, plural, partikular-individual, serba banyak dan tidak tetap.
Mengikuti ajaran gurunya (Socrates), Plato memberi contoh, “sekuntum bunga yang indah”. Sekuntum bunga adalah dunia partikular-individual, sesuatu yang nampak inderawi. Indah adalah dunia ide. Jika ide “indah” berpartisipasi terhadap sekuntum bunga, maka kita mengatakan “sekuntum bunga yang indah”. Dan jika kemudian ide “indah” tidak lagi berpartisipasi kepada bunga tersebut, oleh karena bunga itu telah menjadi layu dan rusak, maka terjadilah perubahan. Akan tetapi, apa yang sebenarnya berubah bukanlah ide “indah” melainkan sekuntum bunga itulah yang berubah. Ide “indah” tidak pernah berubah sebagaimana ide “tidak indah” juga tidak berubah. Ide-ide akan tetap demikian abadi dan tidak berubah. Yang berubah adalah sekuntum bunganya, sesuatu yang particular, sesuatu yang nampak di mata kita.
Terhadap pertanyaan mengenai di mana ide itu berada, Plato menjawab bahwa ide itu berada di alam Tuhan (Divine Realm), dan di alam itu manusia telah mengenal ide-ide dan setelah lahir ke dunia, manusia tinggal mengingat apa yang telah dikenalnya di alam ide tersebut. Manusia telah membawa ide bawaan (innate idea) sebelum lahir ke dunia ini.
Menurut Plato, ide itu ditangkap oleh akal-rasio dan bukan oleh indera, sebaliknya, dunia yang nampak di hadapan kita ini ditangkap oleh indera. Dan pengetahuan yang dihasilkan oleh rasio lebih tinggi nilainya dari yang dihasilkan oleh indera, karena obyek pengetahuan indera adalah obyek yang slalu berubah dan tidak tetap. Pengetahuan yang dihasilkan oleh rasio ia sebut dengan episteme atau genuine knowledge sedangkan yang dihasilkan oleh indera ia sebut dengan opinion. Karena itulah, Plato disebut sebagai pelopor aliran Rasionalisme-Idealisme.
Dalam doktrinnya tentang ide, Plato sendiri memberikan padanan makna ide dengan forms, concept, pattern (pola) dan semakna dengan “universal”. Wujud meja atau temat tidur sebagimana kita saksikan di alam empirik ini, tak lain melainkan imitasi dari pola atau bentuk yang telah ada di alam ide.
Tradisi platonis ini berkembang di kalangan kaum mutakalimin dan filsof muslim serta para skolastik Kristen. Dengan bantuan akal rasio, mereka melakukan kajian terhadap ide-ide atau konsep-konsep keagamaan yang acuannya dari kitab suci. Agama dijelaskan dengan epistemologi Idealisme dan Rasionalisme dan hasilnya sebagimana kita ketahui adalah tesa-tesa keagamaan yang dikema dengan logika filsafat. Memang terjadi pro dan kontra terhadap pendekatan filsafat ini, akan tetapi ini tidak melenyapkan warisan mereka yang telah tersimpan dalam almari peradaban atau menghilangkan semangat generasi berikut dari kajian filsafat. Inilah karir abad skolastik di mana filsafat bertemu dengan doktrin agama.
Di abad modern, melalui tangan Descrates, doktrn platonis dikembangkan dengan mengajukan kriteria untuk menilai ide; kriteria itu adalah clear & distinct, jelas dan terjarak (terpisah). Satu ide dinyatakan benar jika memenuhi kriteria ini, artinya ide itu jelas bisa diangkap, dimengerti dan dijelaskan oleh rasio dan terpisah di mana satu ide berbeda dari lainnya dan terpisah dari subjek. Ide tentang panas, menurut Descrates, secara bisa jelas ditangkap oleh rasio dengan dukungan empirik, dan ide tentang panas itu tidak muncul dari diri subjek melainkan karena sesuatu yang datang dari luar diri, baha di luar diri subjek memang ada api yang meyebabkan muncul ide “panas”. Singkatnya, ide yang masuk ke dalam diri subyek datang dari dunia obyek luar diri.
Argumen inilah yang kemudian digunakan oleh Descrates untuk menjelaskan ide “adanya Tuhan”. Ide ini tidak muncul dari dalam diri subyek melainkan bersumber dari wujud yang infinite (Tuhan) di luar diri subyek. Karena Tuhan adalah Dzat yang infinite, maka ide tentang adanya Dzat yang infinite tidak bisa datang dari hal-hal yang finite (wujud selain Tuhan). Ide tentang adanya Dzat yang infinite haruslah berasal dari Dzat yang infinite. Dengan demikian jelas bahwa Tuhan itu ada, demikian Descrates dalam Discourse on the Method. Descrates mengajukan argumen ini hanya didasarkan pada penalaran rasio tanpa acuan dari Kitab Suci Agama yang dipeluknya. Inilah yang disebut dengan argumen causal proof, (pembuktian melalui sebab munculnya ide) dan bukan argumen ontologi yang lazim dinisbahkan kepada St. Anselmus.
Argumen ontologi ini berlatar belakang dari upaya Anselmus memenuhi permintaan kaum biarawan yang meminta kepadanya membuat argumen untuk membuktikan adanya Tuhan yang tidak dari Kitab Suci melainkan dari permenungan akal pikiran manusia. Isi pokok dari argumen ini demikan, bahwa di dalam akal pikiran kita terdapat ide tantang adanya Dzat yang Maha Besar yang tidak ada lagi yang lebih besar dari zat itu.
Argumen ontologi ini juga dikritik Immanuel Kant dalam karyanya yang terkenal, “The critique of Pure Reason”. Konsep Tuhan ada atau disana ada Tuhan bermakna sama. Kritik model Kantian ini dinukil oleh Iqbal dalam karyanya yang terkenal “The Reconstruction of Modern Thought in Islam”. Ide bahwa di dalam saku baju itu ada uang tiga ratus dolar hanyalah ide yang ada dalam akal pikiran, tidak dapat membuktikan bahwa uang itu benar-benar ada di dalam saku baju itu. Antara ide yang ada dalam pikiran (subyektif) dengan realitas obyektif ada jurang yang tidak bisa dijembatani oleh pemikiran transedetal. Dari tiga pemikir ini, Kant secara eksplisit menganjurkan agar pemikiran filsafat dibalik arahnya, yakni tidak dari subyek ke obyek, melainkan dari obyek ke subyek. Artinya, supaya pemikiran itu obyektif, maka biarlah obyek itu menyatakan dengan sendirinya dan kita hanya berpera mengungkap apa adanya sesuai dengan obyek yang hadir pada kita. Boleh jadi pemikiran-pemikiran yang bersifat subyektif membawa kepada penyimpangan dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada secara nyata.
Mengikuti tesa Kant inilah, Iqbal mencoba mengajukan pemecahan bagaimana agar konsep tentang Tuhan mencapai kriteria yang obyektif, maka biarlah Tuhan sendiri mengungkapkan diri-Nya sendiri melalui firman-Nya, dan bagi kita tidak ada cara lain selain menerima Firman itu. Iqbal menyatakan, biarlah Ego yang infinite menyatakan dirinya sendiri kepada ego yang finite melalui firman-Nya. Iqbal juga menggunakan istilah I am –ness Absolute.
Seperti kita lihat di atas dan uraian-uraian lain di dalam The Critique of Pure Reason, Kant berpandangan bahwa bukan akal murni yang bisa membantu membuktikan adanya Tuhan, melainkan akal praktis. Akal praktis inilah yang disebut the will of human reason atau sering diringkas the will, kehendak, dan ia menunjuk kepada moral. Secara moral, manusia berkehendak untuk memproleh kebahagiaan, dan kebahagiaan yang dikenhendaki oleh setiap manusia hanya akan bisa dicapai secara sempurna pada kehidupan di dunia lain selain dunia sekarang ini. Dan dzat yang bisa memberikan kebahagiaan yang sempurna itu (summum bonum) hanyalah Tuhan. Inilah argumen moral Immanuel Kant dalam usaha membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Di sisi lain ia mengakui bahwa ide tentang adanya Tuhan memang dihasilkan oleh akal murni, akan tetapi akal murni itu sendiri tidak bisa membuktikan atau menolak apakah Tuhan ada ataukah tidak.
Tuhan, kebebasan dan keabadian jiwa, oleh Kant disebut dengan noumena, dan ketiga noumena tersebut diciptakan oleh akal murni, akan tetapi akal murni itu sendiri tidak mampu membuktikan untuk membenarkan numena itu ataukah tidak membenarkannya. Menurut Kant, yang membuktikan keberadaan adalah entitas tersebut, bukan akal murni melainkan akal praktis. Kant melawankan noumena dengan Phenomena, atau dunia yang tampak seperti dalam model Platonis.
Sedikit uraian di atas di samping menurunkan pandangan mengenai pengakuan terhadap keobyektivitasan ide, nampak bahwa ide tantang adanya Tuhan memperoleh perhatian secara kualitatif meskipun kajian pada kesempatan ini hanya mengambil beberapa contoh saja.
2. Tentang Penyaksian (Syahadah) terhadap wujud Tuhan
Meskipun plato secara implisit menyatakan bahwa ide itu ada di alam Tuhan, namun ia tidak memberi contoh konkrit seperti apa ide-ide di alam Tuhan itu sendiri. Ini artinya Plato meninggalkan ruang kosong bagi umat Islam, kekosongan ini dapat diisi dengan menunjuk Al Quran sebagai contoh konkrit, sebab Al Quran bukan ide-ide yang lahir dari Tuhan Allah sendiri yang setelah turun di dunia empirik untuk kepentingan sejarah dan peradaban manusia, ide-ide itu menjelma menjadi lambang-lambang bahasa yang bisa diungkapkan dan ditulis melalui salah seorang hamba yang dipilih oleh-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW.
Kini penulis akan membahas materi pokok ayat di atas yaitu tentang penyaksian manusia kepada Tuhan. Para mufassir mencoba memperkirakan alam di mana terjadi penyaksian ini. Al-Suyuthi, Ibn Katsir dan beberapa mufassir lain menjelaskan bahwa kesaksian manusia ini terjadi di alam fitrah sebelum proses penciptaan jasad manusia dan sebelum roh dimasukkan ke dalam jasad, Allah meminta kesaksian kepadanya. Di alam ini, demikian Ibnu Katsier, manusia telah bersaksi adanya Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diciptakan Allah dalam fitrah ketauhidan, demikian Al Qasimi menjelaskan, di mana manusia di alam itu telah memberi kesaksian tanpa ragu-ragu akan adanya Tuhan. AL-Qurtubi dan beberapa Ulama, demikian kata al-Thabathai, mengajukan konsep “yaum al dzar” (suatu saat ini yang bersifat spiritual) untuk menunjuk saat di mana inti fitrah manusia mengadakan kesaksian ini.
Menurut bahasa, kata “Al-Dzar” bisa diartikan inti dari substansi, dan bisa berarti seberkas sinar, misalnya ketika kita membuka jendela, maka masuklah seberkas sinar melalui jendela itu, akan tetapi harus diakui atau terpaksa harus diakui bahwa amat mungkin ada pihak-pihak tertentu yang sering merasa tidak puas terhadap penjelasan agama, lebih-lebih jika menyangkut istilah yang misteri semisal konsep “al-dzar” di atas dengan dalih penjelasan agama sering tidak bersifat hipotetik, melainkan dogmatik, doktrinal, selalu terkait dengan keyakinan, tidak netral dan tingkat kevalidannya tidak pernah atau tidak mungkin dibuktikan karena derajat metafisiknya yang berifat luar empirik.
Oleh : DR. Khozin Affandi
172. dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)"
Materi pokok dari ayat ini adalah mengenai kesaksian manusia akan adanya wujud Tuhan (syahadah). Akan tetapi kesaksian ini tidak terjadi di alam empirik melainkan di alam lain sebelum manusia menginjak alam empirik yaitu alam sebelum manusia dilahirkan, before born, di alam ini manusia telah mengenal ide, atau innate idea. Karena penyaksian ini terjadi di alam sebelum alam empirik, maka tidak mustahil jika manusia lupa atau tidak menyadari kejadian (penyaksian) tersbut.
Oleh sebab itu, ayat ini mengingatkan ayat keturunan Adam mengenai syahadah tersebut supaya nanti pada hari kiamat mereka tidak mencari alasan untuk mengelakkan diri. Lewat ayat ini manusia diberitahu supaya ia menjadi diri yang memiliki pengetahuan tentang syahadah. Peristiwa yang terjadi di alam praempirik ini bisa dikiaskan dengan alambayi yang baru lahir untuk memulai menjalani kehidupan di alam empirik; meskipun bayi ini sudah hidup di alam empirik, namun kesadaran mereka belum berkembang sehingga bayi itu tidak dapat mengingat apa-apa, bahkan tentang nama dirinya. Baru nanti setelah besar dia diberitahu oleh orang tuanya bahwa ia diberi nama fulan. Anehnya si anak ini percaya begitu saja bahwa ia bernama fulan.
Kita hanya mengajukan logika yang sederhana. Jika di awal alame mpirik saja seseorag tidak menyadari banyak hal yang terjadi pada dirinya ketika masih bayi, apalagi ketika ia masih di alam praempirik. Logika sederhana lainnya ialah; jika berita yang disampaikan oleh orang tentang masa bayinya bisa dipercayainya, apalagi jika verita itu disampaikanoleh Tuhan sang Penguasa Kehidupan Manusia.
Para filosof Yunani kuno, telah membahas pengetahuan manusia, apakah terjadi before born, innate (bawaan), ataukah terjadi setelah di alam empirik. Penulis menurunkan kajian filosofi tentang alamide di bawah ini tidak dimaksudkan untuk tujuan mencocokkan ayat Al Quran dengan tesa-tesa filsafat, apalagi mempersamakan tesa-tesa filsafat sejajar dengan ayat Al Quran, melainkan lebih dimaksudkan untuk membantu memperoleh pemahaman yang bersifat konstekstual. Dalam hal ini, filsafat ditempatkan sebagai sarana atau alat bantu guna mencapai sesuatu dan sesuatu yang hendak dicapai itu adalah pemahaman. Boleh jadi dengan alat bantu ini bisa menghasilkan pemahaman yang baru atau mungkin lebih mantap. Sebagai alat bantu ia bersifat hiipotetik dan ekstrinsik. Ibarat ibu-ibu yang sedang memasak di dapur yang pada saat tertentu membutuhkan pisau, sebagai alat bantu guna mempermudah pekerjaannya, tapi di saat yang lain ia tidak membutuhkan pisau karena obyek yang sedang ditangani memang tidak membutuhkan alat bantu pisau itu.
1. Tentang alam ide.
Adalah para filsof Yunani yang membuka lembaran wacana filsafat dengan mendiskusikan berbagai tema dan isu, dan salah satu tema yang tetap menjadi topik pembicaraan adalah tentang alam ide.
Plato mengkonsepsikan ide sebagai realitas yang sesungguhnya, realitas yang hakiki, sebaliknya, alam yang nampak nyata secara inderawi ini tak lain melainkan dunia bayangan dari alam ide atau alam yang hakiki. Sebagai alam yang sesungguhnya, ide itu tunggal, satu, tetap, tidak berubah dan abadi. Sebaliknya, dunia yang nampak inderawi ini bersifat berubah-uabh, plural, partikular-individual, serba banyak dan tidak tetap.
Mengikuti ajaran gurunya (Socrates), Plato memberi contoh, “sekuntum bunga yang indah”. Sekuntum bunga adalah dunia partikular-individual, sesuatu yang nampak inderawi. Indah adalah dunia ide. Jika ide “indah” berpartisipasi terhadap sekuntum bunga, maka kita mengatakan “sekuntum bunga yang indah”. Dan jika kemudian ide “indah” tidak lagi berpartisipasi kepada bunga tersebut, oleh karena bunga itu telah menjadi layu dan rusak, maka terjadilah perubahan. Akan tetapi, apa yang sebenarnya berubah bukanlah ide “indah” melainkan sekuntum bunga itulah yang berubah. Ide “indah” tidak pernah berubah sebagaimana ide “tidak indah” juga tidak berubah. Ide-ide akan tetap demikian abadi dan tidak berubah. Yang berubah adalah sekuntum bunganya, sesuatu yang particular, sesuatu yang nampak di mata kita.
Terhadap pertanyaan mengenai di mana ide itu berada, Plato menjawab bahwa ide itu berada di alam Tuhan (Divine Realm), dan di alam itu manusia telah mengenal ide-ide dan setelah lahir ke dunia, manusia tinggal mengingat apa yang telah dikenalnya di alam ide tersebut. Manusia telah membawa ide bawaan (innate idea) sebelum lahir ke dunia ini.
Menurut Plato, ide itu ditangkap oleh akal-rasio dan bukan oleh indera, sebaliknya, dunia yang nampak di hadapan kita ini ditangkap oleh indera. Dan pengetahuan yang dihasilkan oleh rasio lebih tinggi nilainya dari yang dihasilkan oleh indera, karena obyek pengetahuan indera adalah obyek yang slalu berubah dan tidak tetap. Pengetahuan yang dihasilkan oleh rasio ia sebut dengan episteme atau genuine knowledge sedangkan yang dihasilkan oleh indera ia sebut dengan opinion. Karena itulah, Plato disebut sebagai pelopor aliran Rasionalisme-Idealisme.
Dalam doktrinnya tentang ide, Plato sendiri memberikan padanan makna ide dengan forms, concept, pattern (pola) dan semakna dengan “universal”. Wujud meja atau temat tidur sebagimana kita saksikan di alam empirik ini, tak lain melainkan imitasi dari pola atau bentuk yang telah ada di alam ide.
Tradisi platonis ini berkembang di kalangan kaum mutakalimin dan filsof muslim serta para skolastik Kristen. Dengan bantuan akal rasio, mereka melakukan kajian terhadap ide-ide atau konsep-konsep keagamaan yang acuannya dari kitab suci. Agama dijelaskan dengan epistemologi Idealisme dan Rasionalisme dan hasilnya sebagimana kita ketahui adalah tesa-tesa keagamaan yang dikema dengan logika filsafat. Memang terjadi pro dan kontra terhadap pendekatan filsafat ini, akan tetapi ini tidak melenyapkan warisan mereka yang telah tersimpan dalam almari peradaban atau menghilangkan semangat generasi berikut dari kajian filsafat. Inilah karir abad skolastik di mana filsafat bertemu dengan doktrin agama.
Di abad modern, melalui tangan Descrates, doktrn platonis dikembangkan dengan mengajukan kriteria untuk menilai ide; kriteria itu adalah clear & distinct, jelas dan terjarak (terpisah). Satu ide dinyatakan benar jika memenuhi kriteria ini, artinya ide itu jelas bisa diangkap, dimengerti dan dijelaskan oleh rasio dan terpisah di mana satu ide berbeda dari lainnya dan terpisah dari subjek. Ide tentang panas, menurut Descrates, secara bisa jelas ditangkap oleh rasio dengan dukungan empirik, dan ide tentang panas itu tidak muncul dari diri subjek melainkan karena sesuatu yang datang dari luar diri, baha di luar diri subjek memang ada api yang meyebabkan muncul ide “panas”. Singkatnya, ide yang masuk ke dalam diri subyek datang dari dunia obyek luar diri.
Argumen inilah yang kemudian digunakan oleh Descrates untuk menjelaskan ide “adanya Tuhan”. Ide ini tidak muncul dari dalam diri subyek melainkan bersumber dari wujud yang infinite (Tuhan) di luar diri subyek. Karena Tuhan adalah Dzat yang infinite, maka ide tentang adanya Dzat yang infinite tidak bisa datang dari hal-hal yang finite (wujud selain Tuhan). Ide tentang adanya Dzat yang infinite haruslah berasal dari Dzat yang infinite. Dengan demikian jelas bahwa Tuhan itu ada, demikian Descrates dalam Discourse on the Method. Descrates mengajukan argumen ini hanya didasarkan pada penalaran rasio tanpa acuan dari Kitab Suci Agama yang dipeluknya. Inilah yang disebut dengan argumen causal proof, (pembuktian melalui sebab munculnya ide) dan bukan argumen ontologi yang lazim dinisbahkan kepada St. Anselmus.
Argumen ontologi ini berlatar belakang dari upaya Anselmus memenuhi permintaan kaum biarawan yang meminta kepadanya membuat argumen untuk membuktikan adanya Tuhan yang tidak dari Kitab Suci melainkan dari permenungan akal pikiran manusia. Isi pokok dari argumen ini demikan, bahwa di dalam akal pikiran kita terdapat ide tantang adanya Dzat yang Maha Besar yang tidak ada lagi yang lebih besar dari zat itu.
Argumen ontologi ini juga dikritik Immanuel Kant dalam karyanya yang terkenal, “The critique of Pure Reason”. Konsep Tuhan ada atau disana ada Tuhan bermakna sama. Kritik model Kantian ini dinukil oleh Iqbal dalam karyanya yang terkenal “The Reconstruction of Modern Thought in Islam”. Ide bahwa di dalam saku baju itu ada uang tiga ratus dolar hanyalah ide yang ada dalam akal pikiran, tidak dapat membuktikan bahwa uang itu benar-benar ada di dalam saku baju itu. Antara ide yang ada dalam pikiran (subyektif) dengan realitas obyektif ada jurang yang tidak bisa dijembatani oleh pemikiran transedetal. Dari tiga pemikir ini, Kant secara eksplisit menganjurkan agar pemikiran filsafat dibalik arahnya, yakni tidak dari subyek ke obyek, melainkan dari obyek ke subyek. Artinya, supaya pemikiran itu obyektif, maka biarlah obyek itu menyatakan dengan sendirinya dan kita hanya berpera mengungkap apa adanya sesuai dengan obyek yang hadir pada kita. Boleh jadi pemikiran-pemikiran yang bersifat subyektif membawa kepada penyimpangan dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ada secara nyata.
Mengikuti tesa Kant inilah, Iqbal mencoba mengajukan pemecahan bagaimana agar konsep tentang Tuhan mencapai kriteria yang obyektif, maka biarlah Tuhan sendiri mengungkapkan diri-Nya sendiri melalui firman-Nya, dan bagi kita tidak ada cara lain selain menerima Firman itu. Iqbal menyatakan, biarlah Ego yang infinite menyatakan dirinya sendiri kepada ego yang finite melalui firman-Nya. Iqbal juga menggunakan istilah I am –ness Absolute.
Seperti kita lihat di atas dan uraian-uraian lain di dalam The Critique of Pure Reason, Kant berpandangan bahwa bukan akal murni yang bisa membantu membuktikan adanya Tuhan, melainkan akal praktis. Akal praktis inilah yang disebut the will of human reason atau sering diringkas the will, kehendak, dan ia menunjuk kepada moral. Secara moral, manusia berkehendak untuk memproleh kebahagiaan, dan kebahagiaan yang dikenhendaki oleh setiap manusia hanya akan bisa dicapai secara sempurna pada kehidupan di dunia lain selain dunia sekarang ini. Dan dzat yang bisa memberikan kebahagiaan yang sempurna itu (summum bonum) hanyalah Tuhan. Inilah argumen moral Immanuel Kant dalam usaha membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Di sisi lain ia mengakui bahwa ide tentang adanya Tuhan memang dihasilkan oleh akal murni, akan tetapi akal murni itu sendiri tidak bisa membuktikan atau menolak apakah Tuhan ada ataukah tidak.
Tuhan, kebebasan dan keabadian jiwa, oleh Kant disebut dengan noumena, dan ketiga noumena tersebut diciptakan oleh akal murni, akan tetapi akal murni itu sendiri tidak mampu membuktikan untuk membenarkan numena itu ataukah tidak membenarkannya. Menurut Kant, yang membuktikan keberadaan adalah entitas tersebut, bukan akal murni melainkan akal praktis. Kant melawankan noumena dengan Phenomena, atau dunia yang tampak seperti dalam model Platonis.
Sedikit uraian di atas di samping menurunkan pandangan mengenai pengakuan terhadap keobyektivitasan ide, nampak bahwa ide tantang adanya Tuhan memperoleh perhatian secara kualitatif meskipun kajian pada kesempatan ini hanya mengambil beberapa contoh saja.
2. Tentang Penyaksian (Syahadah) terhadap wujud Tuhan
Meskipun plato secara implisit menyatakan bahwa ide itu ada di alam Tuhan, namun ia tidak memberi contoh konkrit seperti apa ide-ide di alam Tuhan itu sendiri. Ini artinya Plato meninggalkan ruang kosong bagi umat Islam, kekosongan ini dapat diisi dengan menunjuk Al Quran sebagai contoh konkrit, sebab Al Quran bukan ide-ide yang lahir dari Tuhan Allah sendiri yang setelah turun di dunia empirik untuk kepentingan sejarah dan peradaban manusia, ide-ide itu menjelma menjadi lambang-lambang bahasa yang bisa diungkapkan dan ditulis melalui salah seorang hamba yang dipilih oleh-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW.
Kini penulis akan membahas materi pokok ayat di atas yaitu tentang penyaksian manusia kepada Tuhan. Para mufassir mencoba memperkirakan alam di mana terjadi penyaksian ini. Al-Suyuthi, Ibn Katsir dan beberapa mufassir lain menjelaskan bahwa kesaksian manusia ini terjadi di alam fitrah sebelum proses penciptaan jasad manusia dan sebelum roh dimasukkan ke dalam jasad, Allah meminta kesaksian kepadanya. Di alam ini, demikian Ibnu Katsier, manusia telah bersaksi adanya Tuhan Yang Maha Esa. Manusia diciptakan Allah dalam fitrah ketauhidan, demikian Al Qasimi menjelaskan, di mana manusia di alam itu telah memberi kesaksian tanpa ragu-ragu akan adanya Tuhan. AL-Qurtubi dan beberapa Ulama, demikian kata al-Thabathai, mengajukan konsep “yaum al dzar” (suatu saat ini yang bersifat spiritual) untuk menunjuk saat di mana inti fitrah manusia mengadakan kesaksian ini.
Menurut bahasa, kata “Al-Dzar” bisa diartikan inti dari substansi, dan bisa berarti seberkas sinar, misalnya ketika kita membuka jendela, maka masuklah seberkas sinar melalui jendela itu, akan tetapi harus diakui atau terpaksa harus diakui bahwa amat mungkin ada pihak-pihak tertentu yang sering merasa tidak puas terhadap penjelasan agama, lebih-lebih jika menyangkut istilah yang misteri semisal konsep “al-dzar” di atas dengan dalih penjelasan agama sering tidak bersifat hipotetik, melainkan dogmatik, doktrinal, selalu terkait dengan keyakinan, tidak netral dan tingkat kevalidannya tidak pernah atau tidak mungkin dibuktikan karena derajat metafisiknya yang berifat luar empirik.
Kamis, 18 Februari 2010
TASAWUF: PARADIGMA DAN LOGIKA
(Sebuah Renungan Awal)
oleh: A.Khozin Afandi
A. Paradigma
Kalau kita membicarakan tasawuf secara kritik pertanyaan pertama yang muncul adalah tentang apakah tasawuf sama dengan akhlak ataukah berbeda. Jika sama, mengapa ia tetap dinamakan tasawuf. Tetapi jika berbeda, pertanyaannya menjadi demikian “adakah perbedaan yang substansial antara keduanya”? Persoalan lainnya adalah mengenai apakah tasawuf memberikan peran secara proporsional terhadap logika rasional ataukah tidak, ataukah ia hanya mengandalkan pada logika tekstual. Melalui paradigma dan logika, renungan ini mencoba memberikan jawaban atas persoalan di atas yang, tentu saja, bersifat hipotetik dan tentatif, atau sebuah jawaban alternatif.
Pada mulanya konsep paradigma yang menjadi demikian populer diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Melalui konsep ini, ia membuat analisis kritik terhadap anggapan yang lazim tentang perkembangan ilmu secara kumulatif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa perkembangan utama dan penting dari ilmu pengetahuan itu akibat dari revolusi, sebuah wawasan baru yang tidak lazim dikenal oleh para pemikir kontemporer. Konsep ini kemudian diaplikasikan untuk sosiologi antara lain oleh Friedrichs dan Ritzer. Menurut keduanya, paradigma adalah anggapan dasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) dalam suatu disiplin dan bagaimana aturan-aturannya atau cara kerja untuk menjawab pokok persoalan tersebut. George Ritzer mengembangkan konsep ini untuk memandang sosiologi yang dianggapnya multi paradigma. Sosiologi Durkheim, misalnya, memfokuskan pada fakta sosial menurut cara kerja ilmu natural dengan metode positivisme, yakni mencari fakta yang pasti dan merumuskan hukum. Sosiologi Weber memfokuskan pada tindakan sosial dengan cara kerja hermeneutik yang menekankan metode verstehen yang pernah diajukan oleh Dilthey. Dengan paradigma, pokok persoalan dari sebuah disiplin serta cara kerjanya menjadi jelas dan terpilah. Sebuah disiplin ibarat sebuah wilayah yang memiliki otonomi khas yang ditengarai oleh kriteria substantif-ontologis tentang apa yang manjadi pokok persoalannya, dan kriteria epistemologis-metodologis tentang bagaimana cara kerjanya yang tepat untuk diterapkan baginya.
Kini, paradigma itu diletakkan sebagai lensa pandang untuk melihat tasawuf. Tentu pertanyaan yang muncul adalah tentang apa yang menjadi pokok persoalan tasawuf, dan tentang bagaimana cara kerjanya. Ini merupakan pertanyaan utama yang harus dijawab jika tasawuf hendak dibedakan dari akhlak. Secara teoritis, ada sementara pendapat yang memandang tasawuf itu bagian dari ilmu akhlak dengan alasan karena akhlak merupakan disiplin yang mencakup aturan-aturan mengenai hubungan hamba dengan Tuhannya seperti sabar, tawakkal, taubah, mahabbah, khusyu’, dzikir dengan memperbanyak menyebut nama Allah dan lain-lain serta hubungan sesama manusia. Dengan demikian maka tasawuf adalah akhlak itu sendiri. Dalam pengertian semacam ini, sudah tentu, orang tidak lagi tergerak berusaha menemukan pokok persoalan yang khas tasawuf yang terpilah dan terpisah dari disiplin akhlak yang membedakannya secara substansial. Atau orang tidak lagi mempertanyakan tentang mengapa tasawuf disebut dengan tasawuf dan tidak disebut saja dengan akhlak. Sebaliknya, jika tasawuf diyakini memiliki pokok persoalan yang berbeda dari ilmu akhlak sehingga absah diangap sebagai satu disiplin tersendiri maka tuntutan yang diajukan kepadanya adalah keharusan menemukan pokok persoalan yang khas tasawuf tersebut. Dengan ditemukan pokok persoalan yang khas tasawuf maka keberadaan tasawuf sebagai satu disiplin menjadi mantap.
Apakah pokok persoalan tasawuf yang tidak menjadi garapan akhlak? Seperti lazim diketahui bahwa akhlak mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya (hablun minal-lah) dan hubungan hamba dengan sesamanya (hablun minan-nas). Pengertian semacam ini tidak salah namun ia belum memperlihatkan adanya materi pokok yang membedakan tasawuf dari akhlak. Di sinilah terjadi kekaburan wilayah teoritik antara keduanya. Akhlak mengatur hablun minal-lah, dan tasawuf juga menekankan hubungan dengan Allah, lalu apa pokok masalah yang substansial yang membedakan antar keduanya? Jika pertanyaan ini tidak atau belum terjawab maka pokok persoalan tasawuf pun setiap kali akan muncul.
oleh: A.Khozin Afandi
A. Paradigma
Kalau kita membicarakan tasawuf secara kritik pertanyaan pertama yang muncul adalah tentang apakah tasawuf sama dengan akhlak ataukah berbeda. Jika sama, mengapa ia tetap dinamakan tasawuf. Tetapi jika berbeda, pertanyaannya menjadi demikian “adakah perbedaan yang substansial antara keduanya”? Persoalan lainnya adalah mengenai apakah tasawuf memberikan peran secara proporsional terhadap logika rasional ataukah tidak, ataukah ia hanya mengandalkan pada logika tekstual. Melalui paradigma dan logika, renungan ini mencoba memberikan jawaban atas persoalan di atas yang, tentu saja, bersifat hipotetik dan tentatif, atau sebuah jawaban alternatif.
Pada mulanya konsep paradigma yang menjadi demikian populer diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Melalui konsep ini, ia membuat analisis kritik terhadap anggapan yang lazim tentang perkembangan ilmu secara kumulatif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa perkembangan utama dan penting dari ilmu pengetahuan itu akibat dari revolusi, sebuah wawasan baru yang tidak lazim dikenal oleh para pemikir kontemporer. Konsep ini kemudian diaplikasikan untuk sosiologi antara lain oleh Friedrichs dan Ritzer. Menurut keduanya, paradigma adalah anggapan dasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan (subject matter) dalam suatu disiplin dan bagaimana aturan-aturannya atau cara kerja untuk menjawab pokok persoalan tersebut. George Ritzer mengembangkan konsep ini untuk memandang sosiologi yang dianggapnya multi paradigma. Sosiologi Durkheim, misalnya, memfokuskan pada fakta sosial menurut cara kerja ilmu natural dengan metode positivisme, yakni mencari fakta yang pasti dan merumuskan hukum. Sosiologi Weber memfokuskan pada tindakan sosial dengan cara kerja hermeneutik yang menekankan metode verstehen yang pernah diajukan oleh Dilthey. Dengan paradigma, pokok persoalan dari sebuah disiplin serta cara kerjanya menjadi jelas dan terpilah. Sebuah disiplin ibarat sebuah wilayah yang memiliki otonomi khas yang ditengarai oleh kriteria substantif-ontologis tentang apa yang manjadi pokok persoalannya, dan kriteria epistemologis-metodologis tentang bagaimana cara kerjanya yang tepat untuk diterapkan baginya.
Kini, paradigma itu diletakkan sebagai lensa pandang untuk melihat tasawuf. Tentu pertanyaan yang muncul adalah tentang apa yang menjadi pokok persoalan tasawuf, dan tentang bagaimana cara kerjanya. Ini merupakan pertanyaan utama yang harus dijawab jika tasawuf hendak dibedakan dari akhlak. Secara teoritis, ada sementara pendapat yang memandang tasawuf itu bagian dari ilmu akhlak dengan alasan karena akhlak merupakan disiplin yang mencakup aturan-aturan mengenai hubungan hamba dengan Tuhannya seperti sabar, tawakkal, taubah, mahabbah, khusyu’, dzikir dengan memperbanyak menyebut nama Allah dan lain-lain serta hubungan sesama manusia. Dengan demikian maka tasawuf adalah akhlak itu sendiri. Dalam pengertian semacam ini, sudah tentu, orang tidak lagi tergerak berusaha menemukan pokok persoalan yang khas tasawuf yang terpilah dan terpisah dari disiplin akhlak yang membedakannya secara substansial. Atau orang tidak lagi mempertanyakan tentang mengapa tasawuf disebut dengan tasawuf dan tidak disebut saja dengan akhlak. Sebaliknya, jika tasawuf diyakini memiliki pokok persoalan yang berbeda dari ilmu akhlak sehingga absah diangap sebagai satu disiplin tersendiri maka tuntutan yang diajukan kepadanya adalah keharusan menemukan pokok persoalan yang khas tasawuf tersebut. Dengan ditemukan pokok persoalan yang khas tasawuf maka keberadaan tasawuf sebagai satu disiplin menjadi mantap.
Apakah pokok persoalan tasawuf yang tidak menjadi garapan akhlak? Seperti lazim diketahui bahwa akhlak mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya (hablun minal-lah) dan hubungan hamba dengan sesamanya (hablun minan-nas). Pengertian semacam ini tidak salah namun ia belum memperlihatkan adanya materi pokok yang membedakan tasawuf dari akhlak. Di sinilah terjadi kekaburan wilayah teoritik antara keduanya. Akhlak mengatur hablun minal-lah, dan tasawuf juga menekankan hubungan dengan Allah, lalu apa pokok masalah yang substansial yang membedakan antar keduanya? Jika pertanyaan ini tidak atau belum terjawab maka pokok persoalan tasawuf pun setiap kali akan muncul.
Selasa, 16 Februari 2010
lanjutan Fenomena Perahu Nuh
Selanjutnya mengenai penegasan/pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai pintu memasuki kota ilmu, ini menunjukkan bahwa beliaulah yang “terpilih” dapat membawa umat memasuki kota ilmu-nya Nabi SAW. Karena Nabi SAW secara fisik juga manusia biasa yang pada saatnya pasti meninggalkan dunia (mati), maka beliau ( berdasarkan petunjuk Tuhan tentunya) melakukan “regenerasi” kepemimpinan.
Kemudiann yang jadi permasalahan baru, mengapa yang terpilih Ali bin Abi Thalib yang konon hanya hamba biasa, bukan para tokoh pemikir ataupun bangsawan yang waktu itu juga banyak didapat (yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sesama mereka)?. Permasalahan inilah yang “seharusnya” dimengerti oleh umat manusia, bahwa Tuhan yang kuasa segala-galanya”. Tidak dapat diprediksi sedikitpun apa yang menjadi keputusanNya. Termasuk ketika akan mengangkat Nabi SAW sebagai utusan-Nya, yang menurut ukuran akal jauh sekali kemampuan intelektual maupun ketokohannya dibanding dengan “elit bangsawan” yang ada pada waktu itu.
Jadi Nabi SAW menghendai Ali sebagai pintu untuk bisa memasuki ilmu yang dibawanya – yang juga jauh sama sekali dengan prediksi para tokoh waktu itu –sama halnya dengan pengangkatan Nabi SAW sendiri sebagai utusan-Nya. Hal demikian sudah tentu bukan atas dasar inisiatif Nabi SAW sendiri, melainkan, tentu saja atas petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa harus diperdebatkan (waktu itu dan apalagi sekarang?)
Disamping penegasan sebagai “pintu menuju Tuhan” dilengkapi pula dengan gelar khusu untuk mengokohkan kedudukan Ali, di antaranya “
• Kamu (Ali) adalah bagian dariku (Nabi) dan aku (Nabi) adalah bagian darimu (Ali)
• Dagingmu (Ali) adalah dagingku (Nabi)
• Darahmu (Ali) adalah darahku (Nabi)
• Rohmu (Ali) adalah rohku (Nabi)
• Rahasiamu (Ali) adalah rahasiaku (Nabi)
• Penjelasanmu (Ali) adalah penjelasanku (Nabi)
• Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali)dan celakalah orang yang menolakmu
• Beruntunglah orang yang mencintaimu (Ali) dan merugilah orang yang memusuhimu
• Sejahteralah orang yang mengikutimu (Ali) dan binasalah orang yang berpaling darimu.
Dari ke sembilan gelar khusus yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib tersebut bisa dicermati, betapa istimewanya kedudukan beliau dihadapan/disisi Nabi SAW. Sehingga bisa dikatakan kedudukan beliau bagaikan Harun dengan Musa. Atau bagaikan Ibrahim dengan Ismail. Dalam bahasa filsafatnya “satu di dalam dua, dua di dalam satu”. Satu sama lain sangat menguatkan, saling melengkapi, dan bergandengan sangat erat bagaikan sebuah mata rantai.
Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali)dan celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang yang mencintaimu (Ali) dan merugilah orang yang memusuhimu. Sejahteralah orang yang mengikutimu (Ali) dan binasalah orang yang berpaling darimu.
Dari kedua hal di atas, kota ilmu maunpun pintunya, ada sabda Nabi SAW berikutnya juga sangat menentukan. Yaitu “Kamu dan para imam dari anak keturunanmu sesudahku ibarat perahu Nabi Nuh”. Jelasnya antara Ali dan para Imam dari anak keturunan Ali adalah bagaikan perahu Nuh. Perahu yang dapat menyelamatkan umat dari kehancuran, yang memang Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Impelentasinya, setelah Ali wafat akan dilanjutkan oleh para “imam” dari anak keturunan Ali yang berkedudukan sebagai pintu menuju kota ilmu, yang akan melanjutkan tugas dari Nabi SAW sebagai pintu memasuki ilmu beliau. Sudah tentu penunjukkan Ali kepada keturunannya maupun penunjukkan keturunannya kepada keturunan berikutnya lagi dan seterusnya atas dasar petunjuk dari Tuhan. Sama sekali bukan rekayasa maupun inisiatif sendiri. Bukan pula atas dasar musyawarah maupun pilihan suara. Melainkan murni kehendak Yang Maha Kuasa semata. Seperti halnya ketika nabi akan mengangkat Ali sebagai pintu memasuki ilmunya.
Selanjutnya, ”Siapa yang naik di atasnya akan selamat dan siapa yang menolak (tidak naik) akan tenggelam”. Siapa yang mengiktui semua petunjuk dan tuntunan Ali beserta para Imam sesudahnya akan diselamatkan Tuhan, tetapi siapa yang menolaknya akan ditenggelamkan dalam bencana yang memang sudah disiapkan bagi hamba yang mengingkari ayat-ayatnya.
Keberadaan Ali dan para imam dari anak keturunan beliau ini adalah seperti bintang, yang memberi cahaya penerang ketika kegelapan datang. Setiap kali bintang itu tenggelam akan terbit lagi sampai hari kiyamat. Setiap kali para imam itu meninggal dunia akan muncul lagi imam yang lain hingga kiyamat tiba. Kemunculannya sama sekali tidak dapat diprediksi oleh manusia. Sama sekali bukan karenaatas dasar musyawarah ataupun keturunan darah, melainkan memang sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa.
Walhasil, menaiki perahu nabi Nuh ataupun memasuki kota ilmu Nabi SAW, satu-satunya jalan adalah menemukan para imam yang telah di-”nash”-kan Nabi SAW, yang dimulai oleh sayyidina Ali, dilanjutkan Imam Hasan dan Imam Husen, kemudian dilanjutkan para Imam sesudahnya. Tidak akan pernah putus keberadaan (keberlanjutan)nya sampai kiamat. Setiap kali tenggelam (mati) pasti akan muncul lagi sampai kiamat. Kemudian dibarengi dengan mengikuti semua petunjuk dan larangannya, karena di”tangan” beliau-beliaulah segala rahasia memasuki kota ilmu itu berada.
Yang lebih menentukan lagi bahwa hanya perahu beliau-beliaulah yang dapat/bisa membebaskan umat manusia dari berbagai bencana yang melanda bumi – termasuk bumi Nusantara. Baik bencana yang datangnya dari alam semisal tsunami, gempa, meletusnya gunung api, banjir, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, mewabahnya aneka macam penyakit – maupun yang datangnya dari manusianya sendiri, semisal makin maraknya korupsi, mengganasnya kejahatan dan yang mengerikan adalah makin hilangnya rasa kemanusiaan (berbagai bentuk pembunuhan).
Sedangkan wujud perahunya, bisa berupa jamaah, organisasi, gerakan, ataupun berbentuk apapun, yang jelas kesemuanya merupakan ”amar/sunnah” langsung dari ima tersebut.
Sebab kalau ditelusuri, berbagai bencana yang menimpa para umat zaman terdahulu (kaumnya Nabi Luth, kaumnya Firaun, kaumnya Nabi Nuh, dll) penyebabnya hanyasatu. Mereka semua mengingkari seruan/ajakan para utusan-Nya, yang selalu mengada di tengah-tengah umat manusia.
Semoga kita mendapatkan butiran ilmu_nya, dimengertikan apa yang telah menjadi ayat-ayat-Nya, dipertemukan dengan para Imam pilihan-Nya (yang tidak akan pernah ghaib), serta diberi kekuatan untuk menaiki perahunya serta menjelajah kota ilmu-Nya.
Sekian ...
Kemudiann yang jadi permasalahan baru, mengapa yang terpilih Ali bin Abi Thalib yang konon hanya hamba biasa, bukan para tokoh pemikir ataupun bangsawan yang waktu itu juga banyak didapat (yang pada akhirnya menimbulkan kecemburuan sesama mereka)?. Permasalahan inilah yang “seharusnya” dimengerti oleh umat manusia, bahwa Tuhan yang kuasa segala-galanya”. Tidak dapat diprediksi sedikitpun apa yang menjadi keputusanNya. Termasuk ketika akan mengangkat Nabi SAW sebagai utusan-Nya, yang menurut ukuran akal jauh sekali kemampuan intelektual maupun ketokohannya dibanding dengan “elit bangsawan” yang ada pada waktu itu.
Jadi Nabi SAW menghendai Ali sebagai pintu untuk bisa memasuki ilmu yang dibawanya – yang juga jauh sama sekali dengan prediksi para tokoh waktu itu –sama halnya dengan pengangkatan Nabi SAW sendiri sebagai utusan-Nya. Hal demikian sudah tentu bukan atas dasar inisiatif Nabi SAW sendiri, melainkan, tentu saja atas petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mengapa harus diperdebatkan (waktu itu dan apalagi sekarang?)
Disamping penegasan sebagai “pintu menuju Tuhan” dilengkapi pula dengan gelar khusu untuk mengokohkan kedudukan Ali, di antaranya “
• Kamu (Ali) adalah bagian dariku (Nabi) dan aku (Nabi) adalah bagian darimu (Ali)
• Dagingmu (Ali) adalah dagingku (Nabi)
• Darahmu (Ali) adalah darahku (Nabi)
• Rohmu (Ali) adalah rohku (Nabi)
• Rahasiamu (Ali) adalah rahasiaku (Nabi)
• Penjelasanmu (Ali) adalah penjelasanku (Nabi)
• Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali)dan celakalah orang yang menolakmu
• Beruntunglah orang yang mencintaimu (Ali) dan merugilah orang yang memusuhimu
• Sejahteralah orang yang mengikutimu (Ali) dan binasalah orang yang berpaling darimu.
Dari ke sembilan gelar khusus yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib tersebut bisa dicermati, betapa istimewanya kedudukan beliau dihadapan/disisi Nabi SAW. Sehingga bisa dikatakan kedudukan beliau bagaikan Harun dengan Musa. Atau bagaikan Ibrahim dengan Ismail. Dalam bahasa filsafatnya “satu di dalam dua, dua di dalam satu”. Satu sama lain sangat menguatkan, saling melengkapi, dan bergandengan sangat erat bagaikan sebuah mata rantai.
Berbahagialah orang yang patuh kepadamu (Ali)dan celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang yang mencintaimu (Ali) dan merugilah orang yang memusuhimu. Sejahteralah orang yang mengikutimu (Ali) dan binasalah orang yang berpaling darimu.
Dari kedua hal di atas, kota ilmu maunpun pintunya, ada sabda Nabi SAW berikutnya juga sangat menentukan. Yaitu “Kamu dan para imam dari anak keturunanmu sesudahku ibarat perahu Nabi Nuh”. Jelasnya antara Ali dan para Imam dari anak keturunan Ali adalah bagaikan perahu Nuh. Perahu yang dapat menyelamatkan umat dari kehancuran, yang memang Tuhan sendiri yang akan menghancurkannya. Impelentasinya, setelah Ali wafat akan dilanjutkan oleh para “imam” dari anak keturunan Ali yang berkedudukan sebagai pintu menuju kota ilmu, yang akan melanjutkan tugas dari Nabi SAW sebagai pintu memasuki ilmu beliau. Sudah tentu penunjukkan Ali kepada keturunannya maupun penunjukkan keturunannya kepada keturunan berikutnya lagi dan seterusnya atas dasar petunjuk dari Tuhan. Sama sekali bukan rekayasa maupun inisiatif sendiri. Bukan pula atas dasar musyawarah maupun pilihan suara. Melainkan murni kehendak Yang Maha Kuasa semata. Seperti halnya ketika nabi akan mengangkat Ali sebagai pintu memasuki ilmunya.
Selanjutnya, ”Siapa yang naik di atasnya akan selamat dan siapa yang menolak (tidak naik) akan tenggelam”. Siapa yang mengiktui semua petunjuk dan tuntunan Ali beserta para Imam sesudahnya akan diselamatkan Tuhan, tetapi siapa yang menolaknya akan ditenggelamkan dalam bencana yang memang sudah disiapkan bagi hamba yang mengingkari ayat-ayatnya.
Keberadaan Ali dan para imam dari anak keturunan beliau ini adalah seperti bintang, yang memberi cahaya penerang ketika kegelapan datang. Setiap kali bintang itu tenggelam akan terbit lagi sampai hari kiyamat. Setiap kali para imam itu meninggal dunia akan muncul lagi imam yang lain hingga kiyamat tiba. Kemunculannya sama sekali tidak dapat diprediksi oleh manusia. Sama sekali bukan karenaatas dasar musyawarah ataupun keturunan darah, melainkan memang sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa.
Walhasil, menaiki perahu nabi Nuh ataupun memasuki kota ilmu Nabi SAW, satu-satunya jalan adalah menemukan para imam yang telah di-”nash”-kan Nabi SAW, yang dimulai oleh sayyidina Ali, dilanjutkan Imam Hasan dan Imam Husen, kemudian dilanjutkan para Imam sesudahnya. Tidak akan pernah putus keberadaan (keberlanjutan)nya sampai kiamat. Setiap kali tenggelam (mati) pasti akan muncul lagi sampai kiamat. Kemudian dibarengi dengan mengikuti semua petunjuk dan larangannya, karena di”tangan” beliau-beliaulah segala rahasia memasuki kota ilmu itu berada.
Yang lebih menentukan lagi bahwa hanya perahu beliau-beliaulah yang dapat/bisa membebaskan umat manusia dari berbagai bencana yang melanda bumi – termasuk bumi Nusantara. Baik bencana yang datangnya dari alam semisal tsunami, gempa, meletusnya gunung api, banjir, kebakaran, tanah longsor, kekeringan, mewabahnya aneka macam penyakit – maupun yang datangnya dari manusianya sendiri, semisal makin maraknya korupsi, mengganasnya kejahatan dan yang mengerikan adalah makin hilangnya rasa kemanusiaan (berbagai bentuk pembunuhan).
Sedangkan wujud perahunya, bisa berupa jamaah, organisasi, gerakan, ataupun berbentuk apapun, yang jelas kesemuanya merupakan ”amar/sunnah” langsung dari ima tersebut.
Sebab kalau ditelusuri, berbagai bencana yang menimpa para umat zaman terdahulu (kaumnya Nabi Luth, kaumnya Firaun, kaumnya Nabi Nuh, dll) penyebabnya hanyasatu. Mereka semua mengingkari seruan/ajakan para utusan-Nya, yang selalu mengada di tengah-tengah umat manusia.
Semoga kita mendapatkan butiran ilmu_nya, dimengertikan apa yang telah menjadi ayat-ayat-Nya, dipertemukan dengan para Imam pilihan-Nya (yang tidak akan pernah ghaib), serta diberi kekuatan untuk menaiki perahunya serta menjelajah kota ilmu-Nya.
Sekian ...
Jumat, 12 Februari 2010
FENOMENA PERAHU NABI NUH DAN CARA MENAIKINYA
Oleh : Roni M. Jamaludin
Menaiki perahu Nabi Nuh ..? Ah, mustahil terjadi. Nabi Nuh kan hidupnya sudah ratusan tahun yang lalu, mana mungkin kita bisa menaiki perahunya!! Apalagi wujud perahunya sekarang tidak ada (belum ditemukan). Terus perahunya kayak apa, dimana letaknya, bagaimana bisa menaikinya, bukankah pula seharusnya sudah hancur ditelan jaman? Dan seterusnya-dan seterusnya.
Begitulah kiranya ketika secara sekilas membaca judul di atas. Dan, secara spontan pula akan berkesimpulan bahwa hal tersebut “mustahil” terjadi. Apalagi pandangan logika juga sangat tidak mendukung. Bahkan dapat dikatakan suatu hal yang sangat imposible.
Tetapi, ketika membaca sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-Hakim dan Adz Dzahabi, segala ketidakmungkinan di atas akan terjawab dengan sendirinya. Hadits tersebut adalah :
“Aku adalah kotanya ilmu dan kamu Ya Ali adalah pintunya. Dan janganlah masuk kota kecuali dengan lewat pintunya. Berdustalah orang yang mengatakan cinta kepadaku tetapi membenci kamu karena kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Dagingmu adalah dagingku, darahmu adalah darahku, rohmu adalah rohku, rahasiamu adalah rahasiaku, penjelasanmu adalah penjelasanku. Berbahagialah orang yang patuh kepadamu dan celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang yang mencintaimu dan merugilah orang yang memusuhimu.Sejahteralah orang yang mengikutimu dan binasalah orang yang berpaling darimu.
Kamu dan para imam dari keturunanmu sesudahku ibarat perahu nabi Nuh; siapa yang naik di atasnya selamat, dan siapa yang menolak (tidak mau mengiktu seruannya) akan tenggelam. Kamu semua seperti bintang ; setiap kali bintang itu tenggelam, terbit lagi bintang sampai hari kiyamat”
Menaiki perahu Nabi Nuh ..? Ah, mustahil terjadi. Nabi Nuh kan hidupnya sudah ratusan tahun yang lalu, mana mungkin kita bisa menaiki perahunya!! Apalagi wujud perahunya sekarang tidak ada (belum ditemukan). Terus perahunya kayak apa, dimana letaknya, bagaimana bisa menaikinya, bukankah pula seharusnya sudah hancur ditelan jaman? Dan seterusnya-dan seterusnya.
Begitulah kiranya ketika secara sekilas membaca judul di atas. Dan, secara spontan pula akan berkesimpulan bahwa hal tersebut “mustahil” terjadi. Apalagi pandangan logika juga sangat tidak mendukung. Bahkan dapat dikatakan suatu hal yang sangat imposible.
Tetapi, ketika membaca sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, al-Hakim dan Adz Dzahabi, segala ketidakmungkinan di atas akan terjawab dengan sendirinya. Hadits tersebut adalah :
“Aku adalah kotanya ilmu dan kamu Ya Ali adalah pintunya. Dan janganlah masuk kota kecuali dengan lewat pintunya. Berdustalah orang yang mengatakan cinta kepadaku tetapi membenci kamu karena kamu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Dagingmu adalah dagingku, darahmu adalah darahku, rohmu adalah rohku, rahasiamu adalah rahasiaku, penjelasanmu adalah penjelasanku. Berbahagialah orang yang patuh kepadamu dan celakalah orang yang menolakmu. Beruntunglah orang yang mencintaimu dan merugilah orang yang memusuhimu.Sejahteralah orang yang mengikutimu dan binasalah orang yang berpaling darimu.
Kamu dan para imam dari keturunanmu sesudahku ibarat perahu nabi Nuh; siapa yang naik di atasnya selamat, dan siapa yang menolak (tidak mau mengiktu seruannya) akan tenggelam. Kamu semua seperti bintang ; setiap kali bintang itu tenggelam, terbit lagi bintang sampai hari kiyamat”
Imam Ali Ahlud dzikr
oleh : Dr. A. Chozin Affandi
Dalam khazanah Islam, kata Imam digunakan untuk mensifati seorang yang ahli ilmu agama seperti Imam al-Asy’ari, Imam al-Maturidi, Imam al-Ghazali, Imam al haramain, Imam as-Syafi’i, dan –lain-lain. Imam dalampengertian inilah yang kita pakai untuk memahami Imam Ali karena beliau disepakati bersama oleh kalangan Sunni maupun Syi’i sebagai acuan utama dalam tasawuf.
Ketika turun ayat tentang ahlu adz-dhikr, yakni “fas aluu ahlad-dhikri in kuntum laa ta’lamuun” Imam ‘Ali bin Abi Thalib berkata : “Kami adalah ahlud-dhikri. Penafsiran Imam Ali tentang ahlud-dhikrr ini terdapat dalam kitab tafsir at-Thabari.
Dalam Q.S Al-Anbiya : 8,
At-Thabari (Ibn Jarir at-Thabari, wafat 310 H) menyusun tafsir dengan judul “Jami al-Bayan fi Ta’wil al-Quraan”. Pada mujallid. 9, juzz 17, hal 6 menurunkan satu riwayat yang isinya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, ‘kami adalah ahlud-dhikr”. Teks asli dalam tafsir at-Thabari sbb.
“Dari Ahmad bin Muhammad at-Thusi, dari Abdurrahman bin Shalih dari Musa bin Usman dari Jabir al-Ju’fi, berkata : ketika turun ayat fas aluu ahlad-dhikri in kuntum la ta’lamuun”, berkata Ali bin Abi Thalib, “kami adalah ahlud-dhikr”.
Dalam tata bahasa Arab, kata-kata “kami” (terjemahan dari kata “nahnu”) adalah mutakallimin ma’al ghair). Artinya kata ganti nama “kami” memuat makna lebih dari satu orang (satu subyek). Misal, A adalah Haitsam, seorang guru berkata: ”Kami setiap hari memenuhi kewajiban kami mendidik siswa demi masa depan mereka sebagai generasi bangsa”. Kata kami tersebut tidak hanya untuk diri guru A saja, melainkan sekaligus mewakili teman-teman seprofesi. Demikianlah kata ”kami” yang digunakan oleh Imam Ali, tidak sebatas untuk menunjuk dirinya sendiri melainkan mewakili untuk orang lain yang juga ”ahlud-dhikr”, yakni Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainul Abidin, Imam Muhammad al-Baqir.
Dalam khazanah Islam, kata Imam digunakan untuk mensifati seorang yang ahli ilmu agama seperti Imam al-Asy’ari, Imam al-Maturidi, Imam al-Ghazali, Imam al haramain, Imam as-Syafi’i, dan –lain-lain. Imam dalampengertian inilah yang kita pakai untuk memahami Imam Ali karena beliau disepakati bersama oleh kalangan Sunni maupun Syi’i sebagai acuan utama dalam tasawuf.
Ketika turun ayat tentang ahlu adz-dhikr, yakni “fas aluu ahlad-dhikri in kuntum laa ta’lamuun” Imam ‘Ali bin Abi Thalib berkata : “Kami adalah ahlud-dhikri. Penafsiran Imam Ali tentang ahlud-dhikrr ini terdapat dalam kitab tafsir at-Thabari.
Dalam Q.S Al-Anbiya : 8,
At-Thabari (Ibn Jarir at-Thabari, wafat 310 H) menyusun tafsir dengan judul “Jami al-Bayan fi Ta’wil al-Quraan”. Pada mujallid. 9, juzz 17, hal 6 menurunkan satu riwayat yang isinya bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, ‘kami adalah ahlud-dhikr”. Teks asli dalam tafsir at-Thabari sbb.
“Dari Ahmad bin Muhammad at-Thusi, dari Abdurrahman bin Shalih dari Musa bin Usman dari Jabir al-Ju’fi, berkata : ketika turun ayat fas aluu ahlad-dhikri in kuntum la ta’lamuun”, berkata Ali bin Abi Thalib, “kami adalah ahlud-dhikr”.
Dalam tata bahasa Arab, kata-kata “kami” (terjemahan dari kata “nahnu”) adalah mutakallimin ma’al ghair). Artinya kata ganti nama “kami” memuat makna lebih dari satu orang (satu subyek). Misal, A adalah Haitsam, seorang guru berkata: ”Kami setiap hari memenuhi kewajiban kami mendidik siswa demi masa depan mereka sebagai generasi bangsa”. Kata kami tersebut tidak hanya untuk diri guru A saja, melainkan sekaligus mewakili teman-teman seprofesi. Demikianlah kata ”kami” yang digunakan oleh Imam Ali, tidak sebatas untuk menunjuk dirinya sendiri melainkan mewakili untuk orang lain yang juga ”ahlud-dhikr”, yakni Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali Zainul Abidin, Imam Muhammad al-Baqir.
Kamis, 11 Februari 2010
Khutbah Nabi di Ghadir Qum II
iii). Targhib dan tahdid
Targhib adalah kabar yang menggembirakan (memberikan harapan) sedangkan tahdid adalah kabar yang menyedihkan. Kabar yang menggembirakan ditujukan kepada mereka yang memegang teguh pesan terakhir Nabi Saw yang berasal dari Allah SWT mengenai kepemimpinan sesudah beliau yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib atas kehendak Allah SWT. Sedangkan kabar yang menyedihkan ditujukan kepada mereka yang mengingkari dan menolak pesan terakhir Nabi Saw ini.
iii-a). Targhib
Targhib adalah berita yang menggembirakan yang terkandung di dalam khutbah Nabi Saw ini yang di alamatkan kepada mereka yang mau mengikuti jalan (sunnah) yang di amalkan oleh Imam Ali as. Dalam khutbah ini, Imam Ali tidak mungkin kita pahami sebatas keadaan beliau sebagai pribadi tak ubahnya pribadi-pribadi lain, sebab dengan demikian maka akan tidak menjadi bermakna sama sekali pemberian status dan peran Nabi Saw atas Ali sebagai Imam, sebagai wali sebagai maula sebagai khalifahnya dan sebagai Amirul-mukminin. Pesan Nabi Saw agar kita mengikutinya adalah mengikuti sunnah yang ditetapkan olehnya. Inilah hakekat yang dapat kita tangkap dari pesan Ghadir Khum jika kita berkehendak menempatkan khutbah ini memiliki makna yang relevan dengan keseluruhan teks khutbah. Sebagaimana kita lihat, isi khutbah Rasulullah tidak mengkaitkan status dan peran Imam Ali as dengan kehidupan bernegara atau berpolitik melainkan lebih menekankan pada jalan spiritual yang haq, bertemu Allah, dan beribadah kepadaNya.
Contoh targhib dalam khutbah Rasulullah,
“Ya Allah, berilah kasih sayangmu kepada orang yang mencintai Ali, musuhilah orang yang memusuhi Ali, kutuklah orang yang mengingkari Ali, dan murkailah orang yang menghujat haknya”.
“Dengarlah perintahnya (Ali) niscaya kamu selamat, taatilah niscaya kamu mendapat hidayah, hindarilah apa yang dilarangnya niscaya kamu mendapat petunjuk, dan bersikaplah (berjalanlah) ke arah yang ditunjukannya dan janganlah kamu menyimpang dari jalannya”.
“Barangsiapa yang taat kepada Allah, kepada RasulNya dan kepada Ali dan kepada para Imam sesudahnya yang telah kami tuturkan kepada kamu, maka dia akan memperoleh kebahagiaan yang gemilang”.
“Ketahuilah bahwa dasar (pangkal) amar makruf dan nahi munkar adalah kemauan kalian menerima sabdaku sebagai sesuatu yang final, kemudian kamu mau menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir (di Ghadir Khum ini) dan kamu memerintahnya untuk menerima pesan ini dan melarang mereka menentangnya (mengingkarinya) karena sesungguhnya pesan ini dari Allah dan dari aku; sesungguhnya tidak ada amar makruf dan nahi munkar kecuali dengan bersamaan dengan (adanya) Imam yang maksum”.
Targhib adalah kabar yang menggembirakan (memberikan harapan) sedangkan tahdid adalah kabar yang menyedihkan. Kabar yang menggembirakan ditujukan kepada mereka yang memegang teguh pesan terakhir Nabi Saw yang berasal dari Allah SWT mengenai kepemimpinan sesudah beliau yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib atas kehendak Allah SWT. Sedangkan kabar yang menyedihkan ditujukan kepada mereka yang mengingkari dan menolak pesan terakhir Nabi Saw ini.
iii-a). Targhib
Targhib adalah berita yang menggembirakan yang terkandung di dalam khutbah Nabi Saw ini yang di alamatkan kepada mereka yang mau mengikuti jalan (sunnah) yang di amalkan oleh Imam Ali as. Dalam khutbah ini, Imam Ali tidak mungkin kita pahami sebatas keadaan beliau sebagai pribadi tak ubahnya pribadi-pribadi lain, sebab dengan demikian maka akan tidak menjadi bermakna sama sekali pemberian status dan peran Nabi Saw atas Ali sebagai Imam, sebagai wali sebagai maula sebagai khalifahnya dan sebagai Amirul-mukminin. Pesan Nabi Saw agar kita mengikutinya adalah mengikuti sunnah yang ditetapkan olehnya. Inilah hakekat yang dapat kita tangkap dari pesan Ghadir Khum jika kita berkehendak menempatkan khutbah ini memiliki makna yang relevan dengan keseluruhan teks khutbah. Sebagaimana kita lihat, isi khutbah Rasulullah tidak mengkaitkan status dan peran Imam Ali as dengan kehidupan bernegara atau berpolitik melainkan lebih menekankan pada jalan spiritual yang haq, bertemu Allah, dan beribadah kepadaNya.
Contoh targhib dalam khutbah Rasulullah,
“Ya Allah, berilah kasih sayangmu kepada orang yang mencintai Ali, musuhilah orang yang memusuhi Ali, kutuklah orang yang mengingkari Ali, dan murkailah orang yang menghujat haknya”.
“Dengarlah perintahnya (Ali) niscaya kamu selamat, taatilah niscaya kamu mendapat hidayah, hindarilah apa yang dilarangnya niscaya kamu mendapat petunjuk, dan bersikaplah (berjalanlah) ke arah yang ditunjukannya dan janganlah kamu menyimpang dari jalannya”.
“Barangsiapa yang taat kepada Allah, kepada RasulNya dan kepada Ali dan kepada para Imam sesudahnya yang telah kami tuturkan kepada kamu, maka dia akan memperoleh kebahagiaan yang gemilang”.
“Ketahuilah bahwa dasar (pangkal) amar makruf dan nahi munkar adalah kemauan kalian menerima sabdaku sebagai sesuatu yang final, kemudian kamu mau menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak hadir (di Ghadir Khum ini) dan kamu memerintahnya untuk menerima pesan ini dan melarang mereka menentangnya (mengingkarinya) karena sesungguhnya pesan ini dari Allah dan dari aku; sesungguhnya tidak ada amar makruf dan nahi munkar kecuali dengan bersamaan dengan (adanya) Imam yang maksum”.
Khutbah Nabi di Ghadir Qum I
1.Sumber Data Khutbah Nabi di Ghadir Khum
Data khutbah Nabi ini diambil dari karya DR. Ali Akbar Shadeqi yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Husein Shahab dan diterbitkan oleh Pustaka Pelita, Bandung, cetakan pertama pada April 1998. Ali Akbar Sadeqi juga menjelaskan data khutbah Ghadir khum ini terdapat dalam 18 belas kitab yang ditulis baik oleh ulama kalangan Sunni dan Syi’ah (lihat Ali Akbar Shadeqi; hlm. 19-21).
2. Pentingnya Studi Sejarah
Sejarah, kata Thomas S. Kuhn, penulis karya terkenal “The Structure of Scientific Revolution”, jika lebih dipandang sebagai khazanah daripada sekedar anekdot dan kronologi, dapat menghasilkan perubahan yang menentukan dalam citra pengetahuan.
Perubahan-perubahan interpretasi (penjelasan) di dalam sejarah, Kata Louis Gottschalk, sering disebabkan karena ditemukannya data dari sumbernya yang selama ini hilang atau tersembunyi. Dua teori di atas mengarah kepada makna yang sama, bahwa peluang terjadinya perubahan orientasi (wawasan) amat terbuka dalam memahami sejarah menyusul ditemukannya data sejarah dari sumbernya yang selama ini hilang atau tersembunyi.
Data sejarah umat Islam yang menggambarkan peristiwa penting di masa awal adalah khutbah Nabi Saw di Ghadir Khum ini. Pada dasa warsa tahun 1990 an, diskusi di sekitar masalah Ghadir Khum ini menampakkan kecenderungan yang meningkat meskipun belum naik ke atas permukaan sejarah dan menjadi arus yang dominan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Situasi semacam ini merupakan karunia sejarah bagi kita warga Jama’ah Lil-Muqorrobien untuk ikut mengambil peran dalam usaha menjadikan data Ghadir Khum ini menjadi tema utama dalam wacana peradaban menuju terjadinya tranformasi orientasi (perubahan wawasan). Transformasi macam ini berada pada dataran teoritik dan intelektual, yang pada gilirannya, diharapkan bisa melahirkan perubahan sikap pada dataran praktis dan moral (tingkah laku).
Meminjam model hermeneutika-filsafat Martin Heidegger, bahwa tujuan dari pemahaman terhadap teks (termasuk data sejarah) tidak lagi untuk memperoleh pengetahuan yang obyektif sebagaimana anjuran dari hermeneutik teori model Emilio Bettti, melainkan bertujuan praktis, yakni lahirnya pengetahuan yang relevan yang dapat membuat perubahan bagi seseorang karena menyadari diperolehnya peluang-peluang baru guna membentuk esksistensi diri dan tanggung jawabnya bagi masa depan.
Khutbah Ghadir Khum, jelas, memiliki peluang melahirkan orientasi baru dan dengan demikian juga punya peluang melahirkan eksistensi manusia baru. Khutbah Ghadir Khum ini berpeluang menggugah kesadaran batin seseorang setelah akal sehatnya yang bening dan tanpa prasangka nafsu mengakui keabsahan data ini secara obyektif.
3. Isi Pokok dan Garis besar Khutbah Ghadir Khum
Data khutbah Nabi ini diambil dari karya DR. Ali Akbar Shadeqi yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Husein Shahab dan diterbitkan oleh Pustaka Pelita, Bandung, cetakan pertama pada April 1998. Ali Akbar Sadeqi juga menjelaskan data khutbah Ghadir khum ini terdapat dalam 18 belas kitab yang ditulis baik oleh ulama kalangan Sunni dan Syi’ah (lihat Ali Akbar Shadeqi; hlm. 19-21).
2. Pentingnya Studi Sejarah
Sejarah, kata Thomas S. Kuhn, penulis karya terkenal “The Structure of Scientific Revolution”, jika lebih dipandang sebagai khazanah daripada sekedar anekdot dan kronologi, dapat menghasilkan perubahan yang menentukan dalam citra pengetahuan.
Perubahan-perubahan interpretasi (penjelasan) di dalam sejarah, Kata Louis Gottschalk, sering disebabkan karena ditemukannya data dari sumbernya yang selama ini hilang atau tersembunyi. Dua teori di atas mengarah kepada makna yang sama, bahwa peluang terjadinya perubahan orientasi (wawasan) amat terbuka dalam memahami sejarah menyusul ditemukannya data sejarah dari sumbernya yang selama ini hilang atau tersembunyi.
Data sejarah umat Islam yang menggambarkan peristiwa penting di masa awal adalah khutbah Nabi Saw di Ghadir Khum ini. Pada dasa warsa tahun 1990 an, diskusi di sekitar masalah Ghadir Khum ini menampakkan kecenderungan yang meningkat meskipun belum naik ke atas permukaan sejarah dan menjadi arus yang dominan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Situasi semacam ini merupakan karunia sejarah bagi kita warga Jama’ah Lil-Muqorrobien untuk ikut mengambil peran dalam usaha menjadikan data Ghadir Khum ini menjadi tema utama dalam wacana peradaban menuju terjadinya tranformasi orientasi (perubahan wawasan). Transformasi macam ini berada pada dataran teoritik dan intelektual, yang pada gilirannya, diharapkan bisa melahirkan perubahan sikap pada dataran praktis dan moral (tingkah laku).
Meminjam model hermeneutika-filsafat Martin Heidegger, bahwa tujuan dari pemahaman terhadap teks (termasuk data sejarah) tidak lagi untuk memperoleh pengetahuan yang obyektif sebagaimana anjuran dari hermeneutik teori model Emilio Bettti, melainkan bertujuan praktis, yakni lahirnya pengetahuan yang relevan yang dapat membuat perubahan bagi seseorang karena menyadari diperolehnya peluang-peluang baru guna membentuk esksistensi diri dan tanggung jawabnya bagi masa depan.
Khutbah Ghadir Khum, jelas, memiliki peluang melahirkan orientasi baru dan dengan demikian juga punya peluang melahirkan eksistensi manusia baru. Khutbah Ghadir Khum ini berpeluang menggugah kesadaran batin seseorang setelah akal sehatnya yang bening dan tanpa prasangka nafsu mengakui keabsahan data ini secara obyektif.
3. Isi Pokok dan Garis besar Khutbah Ghadir Khum
Langganan:
Postingan (Atom)